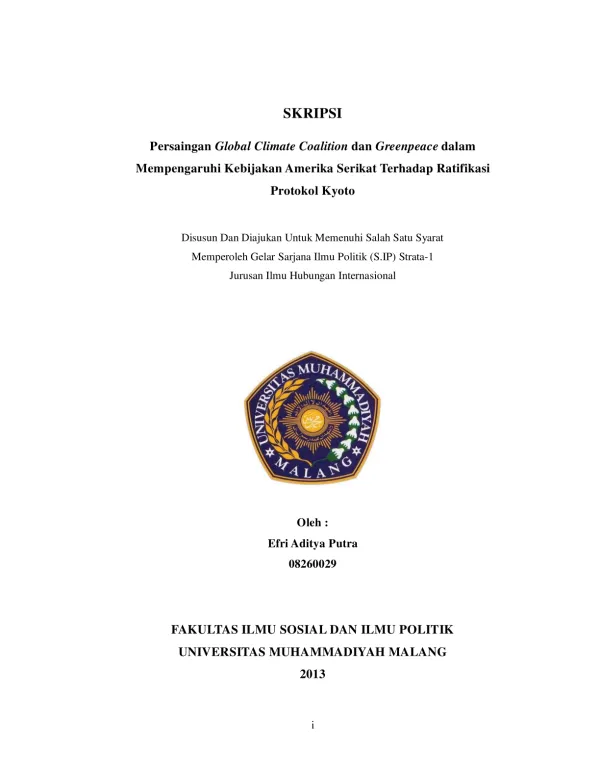
Analisis Persaingan Global Climate Coalition dan Greenpeace dalam Kebijakan AS
Informasi dokumen
| Penulis | Efri Aditya Putra |
| school/university | Universitas Muhammadiyah Malang |
| subject/major | Hubungan Internasional |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| city where the document was published | Malang |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 261.36 KB |
- Persaingan Global
- Kebijakan Lingkungan
- Protokol Kyoto
Ringkasan
I.Abstraksi Abstract
Skripsi ini menganalisis persaingan antara Global Climate Coalition (GCC) dan Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terkait ratifikasi Protokol Kyoto. AS menolak Protokol Kyoto karena kekhawatiran dampak negatif terhadap ekonomi nasional. GCC, didukung oleh perusahaan besar seperti ExxonMobil, berhasil melobi pemerintah AS, terutama di era George W. Bush, untuk menolak ratifikasi. Penelitian ini menggunakan teori Politik-Birokratik Graham T. Allison dan konsep kelompok kepentingan serta kelompok penekan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan ini. The study examines the competition between the Global Climate Coalition and Greenpeace in influencing United States policy regarding the Kyoto Protocol ratification. The US rejected the Kyoto Protocol due to concerns about negative impacts on the national economy. GCC, backed by major corporations such as ExxonMobil, successfully lobbied the US government, particularly during the George W. Bush administration, to reject ratification.
1. Inti Penelitian
Abstraksi dan abstrak penelitian ini secara garis besar menjelaskan fokus utama pada persaingan antara dua kelompok kepentingan, yaitu Global Climate Coalition (GCC) dan Greenpeace, dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terkait ratifikasi Protokol Kyoto. Penolakan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto didorong oleh kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perekonomian negara. GCC, yang didukung oleh dana besar dan diperkuat oleh keanggotaan ExxonMobil serta kedekatannya dengan pemerintahan George W. Bush, memainkan peran kunci dalam mempengaruhi keputusan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif, mengandalkan teori Politik-Birokratik Graham T. Allison, dan menganalisis peran kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam proses pengambilan keputusan di Amerika Serikat. Secara ringkas, penelitian ini menyelidiki bagaimana pengaruh kelompok-kelompok kepentingan tersebut, khususnya GCC dan Greenpeace, terhadap keputusan politik Amerika Serikat, terutama dalam konteks penolakan ratifikasi Protokol Kyoto yang memiliki implikasi besar terhadap isu perubahan iklim global.
2. Protokol Kyoto dan Penolakan AS
Bagian ini menjelaskan Protokol Kyoto sebagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Protokol ini mewajibkan negara-negara Annex I, termasuk Amerika Serikat, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5%. Namun, Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi Protokol Kyoto karena alasan ekonomi, yaitu dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian nasional. Keputusan ini, seperti yang dijelaskan dalam abstrak, dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang berseberangan, yaitu GCC yang menentang dan Greenpeace yang mendukung ratifikasi. Pengaruh GCC yang kuat, khususnya karena dukungan finansial yang besar dan kedekatan dengan pemerintahan AS, menjadi fokus utama penelitian ini dalam memahami bagaimana keputusan politik tersebut terbentuk. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana proses negosiasi dan lobi dilakukan oleh kedua belah pihak.
3. Metodologi dan Kerangka Teori
Metodologi penelitian ini didasarkan pada pendekatan eksplanatif, bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana AS menolak ratifikasi Protokol Kyoto. Penelitian ini memanfaatkan Teori Politik Luar Negeri model Graham T. Allison, khususnya model Politik-Birokratik, untuk menganalisis interaksi antara berbagai aktor dan organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Konsep kelompok kepentingan dan kelompok penekan menjadi kunci dalam memahami dinamika politik di balik penolakan tersebut. Model Politik-Birokratik menekankan pada proses negosiasi dan tawar-menawar antara berbagai aktor, termasuk kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian akan mengungkap bagaimana GCC dan Greenpeace, masing-masing sebagai kelompok penekan yang kuat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pemerintahan AS. Penelitian juga mempertimbangkan sistem pengaruh kebijakan (policy influence system) untuk menjelaskan bagaimana kedua kelompok ini berinteraksi dengan para pengambil kebijakan.
II.Latar Belakang
Penelitian ini berfokus pada penolakan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim, seperti bencana alam yang meningkat di berbagai negara (India, Bangladesh, Mesir, Haiti, dan AS sendiri), mendorong Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi. Namun, AS menolak ratifikasi karena kekhawatiran akan dampak negatif terhadap ekonomi, terutama pada sektor industri seperti otomotif dan energi. Ini memicu persaingan antara pendukung ratifikasi (seperti Greenpeace dan gerakan Kyoto Now) dan penentangnya (seperti GCC).
1. Dampak Perubahan Iklim Global
Bagian latar belakang diawali dengan penjelasan mengenai dampak perubahan iklim yang telah dirasakan oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Disebutkan contoh bencana banjir di India, Bangladesh, dan Mesir akibat naiknya permukaan air laut. Badai Ike di Haiti juga disebutkan sebagai contoh dampak perubahan iklim yang mengakibatkan korban jiwa hingga 600 orang. Amerika Serikat sendiri juga mengalami bencana alam berupa badai yang menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur. Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian serius dunia internasional, yang memicu berbagai upaya untuk menanggulangi perubahan iklim global. Kondisi ini menjadi latar belakang penting bagi penelitian, yang menekankan urgensi isu perubahan iklim dan upaya internasional untuk mengatasinya, termasuk Protokol Kyoto sebagai salah satu instrumen kunci.
2. Konvensi Kerangka Kerja PBB dan Protokol Kyoto
Sebagai respon atas dampak negatif perubahan iklim global, Konferensi Tingkat Tinggi Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Konvensi ini merupakan langkah awal dalam upaya internasional untuk mengatasi masalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses industrialisasi. Kemudian, pada tahun 1997, Protokol Kyoto dirumuskan sebagai kesepakatan yang lebih kuat untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari negara-negara industri maju. Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara industri untuk mengurangi emisi sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990, paling lambat tahun 2012. Penjelasan ini memberikan konteks penting terkait latar belakang munculnya Protokol Kyoto sebagai respons terhadap isu perubahan iklim dan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global, yang menjadi fokus penelitian ini.
3. Penolakan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto
Bagian ini menjelaskan penolakan Amerika Serikat terhadap ratifikasi Protokol Kyoto. Meskipun Amerika Serikat merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar, keputusan untuk menolak ratifikasi didasarkan pada kekhawatiran akan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Ratifikasi Protokol Kyoto, menurut pandangan AS, akan mengharuskan perubahan besar-besaran pada tatanan industri, membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan berpotensi menurunkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penolakan AS terhadap Protokol Kyoto bukanlah semata-mata soal lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan pertimbangan ekonomi dan kepentingan nasional. Hal ini menjadi titik awal bagi penelitian yang akan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini, termasuk peran kelompok kepentingan dan tekanan politik di dalam negeri.
4. Persaingan Kelompok Kepentingan
Latar belakang juga menyinggung adanya dinamika politik di balik keputusan AS untuk menolak ratifikasi Protokol Kyoto. Terdapat persaingan antara kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki pandangan berbeda. Greenpeace, sebagai perwakilan aktivis lingkungan, mendukung ratifikasi Protokol Kyoto karena menganggap AS sebagai salah satu emitor terbesar dan perlu berkontribusi dalam pengurangan emisi. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar di AS, seperti ExxonMobil dan General Motors, yang tergabung dalam Global Climate Coalition (GCC), menentang ratifikasi karena khawatir akan terganggunya kegiatan industri dan penurunan perekonomian. Persaingan antara kedua kelompok ini menjadi fokus utama penelitian, untuk memahami bagaimana mereka mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan AS terkait kebijakan lingkungan dan perubahan iklim.
III.Kerangka Pemikiran
Penelitian ini menggunakan model Politik-Birokratik Graham T. Allison untuk menganalisis bagaimana kelompok kepentingan (interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups) seperti GCC dan Greenpeace mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat. Analisis juga mempertimbangkan sistem pengaruh kebijakan (policy influence system), memperhatikan peran interest influencers dan mass influencers dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi para pembuat kebijakan. Model ini menekankan peran tawar-menawar (bargaining) antar aktor dalam birokrasi dan politik domestik AS dalam menentukan kebijakan terkait Protokol Kyoto.
1. Teori Politik Luar Negeri dan Pengaruh Domestik
Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada studi Hubungan Internasional, khususnya teori politik luar negeri. Disebutkan bahwa politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Penelitian ini berfokus pada faktor internal, khususnya di Amerika Serikat, dalam konteks penolakan ratifikasi Protokol Kyoto. Di negara demokrasi seperti AS, kelompok kepentingan (interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups) memiliki peran penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri. Struktur politik dan ekonomi, kepribadian nasional, budaya, dan ideologi juga turut berperan dalam menentukan politik luar negeri. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor domestik ini, terutama peran kelompok kepentingan dan penekan, mempengaruhi keputusan AS terkait Protokol Kyoto.
2. Model Politik Birokratik Graham T. Allison
Sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini menggunakan model Politik-Birokratik yang dikembangkan oleh Graham T. Allison. Model ini memandang pengambilan keputusan politik luar negeri bukan sebagai proses intelektual yang rasional semata, melainkan sebagai hasil interaksi, penyesuaian, dan perpolitikan antara berbagai aktor dan organisasi di dalam negeri. Keputusan politik luar negeri, menurut model ini, muncul dari proses tawar-menawar (bargaining) antara para pelaku dalam birokrasi dan perpolitikan nasional. Penelitian ini akan menerapkan model ini untuk menganalisis persaingan antara GCC dan Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan AS terhadap Protokol Kyoto, dengan melihat bagaimana masing-masing kelompok melakukan lobi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Sistem pengaruh kebijakan (policy influence system) menjadi bagian penting dalam analisis ini.
3. Konsep Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan
Kerangka pemikiran juga menjelaskan konsep kelompok kepentingan (interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups). Kelompok kepentingan merupakan struktur yang menyalurkan kepentingan anggota masyarakat terhadap sistem politik. Terdapat empat tipe kelompok kepentingan menurut Gabriel Almond: anomik, non-asosiasi, institusional, dan asosiasi. Kelompok penekan, menurut Derbyshire, adalah kelompok yang mewakili suatu kepentingan atau isu tertentu untuk mencapai tujuan dengan memberikan tekanan pada pemerintah. Greenpeace, sebagai contoh kelompok penekan, memperjuangkan isu lingkungan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana GCC dan Greenpeace, sebagai kelompok kepentingan dan penekan, menggunakan berbagai strategi, termasuk lobi, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan Amerika Serikat mengenai ratifikasi Protokol Kyoto. Perbedaan dan persamaan kedua model kelompok ini menjadi bagian penting dalam pengkajian penelitian.
IV.Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif untuk menjelaskan mengapa AS menolak Protokol Kyoto. Penelitian ini membatasi waktu penelitian antara tahun 2001-2009 (masa pemerintahan George W. Bush) dan berfokus pada persaingan antara GCC dan Greenpeace sebagai variabel independen, dan kebijakan AS terhadap ratifikasi Protokol Kyoto sebagai variabel dependen. Analisis dilakukan pada tingkat korelasionis, melihat hubungan antara kelompok-kelompok dan kebijakan yang dihasilkan.
1. Metode Penelitian Eksplanatif
Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif. Metode ini dipilih untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fakta atau kondisi, dalam hal ini penolakan Amerika Serikat terhadap ratifikasi Protokol Kyoto, terjadi. Peneliti akan mengamati hubungan antara variabel-variabel yang telah ditentukan dan menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan antara kelompok kepentingan dan kelompok penekan di Amerika Serikat, khususnya Global Climate Coalition (GCC) dan Greenpeace, serta pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah AS terkait Protokol Kyoto. Dengan metode eksplanatif, penelitian akan berusaha untuk memberikan penjelasan kausalitas dari fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana pengaruh GCC dan Greenpeace terhadap keputusan politik AS.
2. Variabel Penelitian dan Tingkat Analisis
Variabel independen dalam penelitian ini adalah persaingan antara Global Climate Coalition (GCC) dan Greenpeace. Variabel dependennya adalah kebijakan Amerika Serikat terhadap ratifikasi Protokol Kyoto. Penelitian ini menggunakan analisis korelasionis, yang berarti fokus pada hubungan antara variabel independen dan dependen pada tingkat yang sama, yaitu individu atau kelompok. Dengan kata lain, analisis ini akan mengkaji hubungan antara aktivitas GCC dan Greenpeace dengan keputusan politik AS terkait Protokol Kyoto, untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing kelompok tersebut terhadap keputusan akhir. Penggunaan analisis korelasionis menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara dua variabel utama tersebut, bukan untuk membangun hubungan sebab-akibat yang sepenuhnya pasti.
3. Batasan Waktu dan Materi Penelitian
Penelitian ini membatasi waktu penelitian pada periode tahun 2001 sampai 2009, bertepatan dengan masa pemerintahan George W. Bush. Pembatasan waktu ini dilakukan agar penelitian tetap fokus pada fenomena yang diteliti dan mempermudah pengumpulan data. Pembatasan materi juga diterapkan agar pembahasan tetap relevan dengan kerangka penelitian. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara logis, dengan mencari hubungan antara variabel dan konsep-konsep yang telah diidentifikasi. Proses analisis melibatkan pemetaan data ke dalam kategori-kategori tertentu, kemudian mencari hubungan antar data berdasarkan kerangka berpikir yang telah disiapkan. Hal ini memastikan bahwa analisis tetap terstruktur dan terarah pada tujuan penelitian, yaitu menjelaskan pengaruh GCC dan Greenpeace terhadap kebijakan AS terkait Protokol Kyoto.
V.Hipotesis
Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa GCC memiliki pengaruh lebih besar daripada Greenpeace dalam mempengaruhi keputusan AS untuk menolak Protokol Kyoto. GCC menggunakan strategi penyebaran isu negatif dan pendekatan kepada tokoh penting di pemerintahan AS untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini akan menganalisis strategi dan pengaruh kedua kelompok kepentingan tersebut.
1. Kekuatan Global Climate Coalition GCC dibandingkan Greenpeace
Hipotesis penelitian ini mengajukan dugaan sementara bahwa Global Climate Coalition (GCC) memiliki pengaruh yang lebih besar daripada Greenpeace dalam mempengaruhi pengambilan keputusan Pemerintah Amerika Serikat terkait ratifikasi Protokol Kyoto. Dugaan ini didasarkan pada pemahaman awal bahwa GCC, dengan sumber daya finansial yang lebih besar dan kedekatan dengan pemerintahan AS, khususnya di era George W. Bush, memiliki kemampuan yang lebih efektif dalam melobi dan mempengaruhi para pembuat kebijakan. Sebaliknya, meskipun Greenpeace memiliki basis massa yang luas dan pengaruh moral, kekuatannya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah AS dianggap lebih terbatas dibandingkan GCC. Penelitian ini akan menguji hipotesis ini dengan menganalisis strategi dan pengaruh yang digunakan oleh kedua kelompok tersebut.
2. Strategi Pengaruh GCC
Hipotesis lebih lanjut menjelaskan mengenai strategi yang digunakan GCC untuk mempengaruhi keputusan pemerintah AS. GCC diduga menggunakan strategi penyebaran isu negatif terkait dampak ekonomi dari ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan menyebarkan isu-isu tersebut, GCC berusaha untuk menciptakan opini publik yang kurang mendukung ratifikasi dan memberikan tekanan pada pemerintah. Selain itu, GCC juga diduga mendekati orang-orang penting di dalam pemerintahan AS untuk melobi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara langsung. Strategi ini mencerminkan upaya GCC untuk memanfaatkan kekuatan finansial dan hubungan politiknya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan kelompoknya, yaitu menolak ratifikasi Protokol Kyoto. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih detail bagaimana strategi-strategi ini dijalankan dan seberapa efektifnya.
