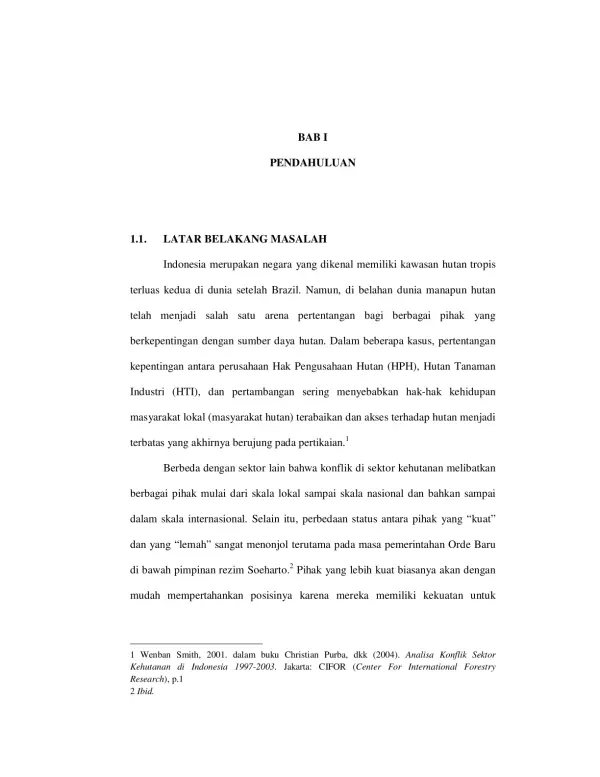
Analisis Konflik dan Pembangunan Sektor Kehutanan di Indonesia
Informasi dokumen
| Penulis | Christian Purba |
| Sekolah | CIFOR (Center For International Forestry Research) |
| Jurusan | Kehutanan/Ilmu Lingkungan |
| Tempat | Jakarta |
| Jenis dokumen | Buku/Analisa |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 794.88 KB |
- konflik kehutanan
- pembangunan ekonomi
- kebijakan Orde Baru
Ringkasan
I.Latar Belakang Masalah Deforestasi di Indonesia Era Orde Baru
Indonesia, negara dengan hutan tropis terluas kedua setelah Brazil, mengalami deforestasi masif pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Konflik kepentingan antara perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, dan masyarakat lokal menyebabkan kerusakan hutan tropis yang meluas. Kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor kayu dan penanaman modal asing (PMA) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, serta Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1970 dan No. 18 Tahun 1975 tentang HPH, mempercepat degradasi hutan. Hal ini berdampak pada kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat.
1. Konflik Kepentingan dan Pertikaian di Sektor Kehutanan
Indonesia memiliki hutan tropis terluas kedua di dunia. Namun, pengelolaan hutan seringkali menimbulkan konflik kepentingan. Persaingan antara perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan sektor pertambangan seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat hutan. Akibatnya, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbatas, memicu pertikaian dan konflik yang kompleks. Konflik ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga meluas hingga tingkat nasional dan internasional. Kekuasaan yang timpang antara pihak yang 'kuat' dan 'lemah', terutama terlihat menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, semakin mempersulit penyelesaian konflik kehutanan. Perbedaan status ini membuat pihak yang lebih kuat cenderung mempertahankan posisinya, sedangkan pihak yang lemah kesulitan memperjuangkan haknya.
2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Orde Baru dan Sektor Kehutanan
Pada awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi berjalan lambat akibat situasi politik dalam negeri yang memburuk. Kondisi ini mengakibatkan rencana pembangunan dan skala perekonomian menjadi terbatas, dan berpotensi meningkatkan inflasi. Prioritas kebijakan stabilitas ekonomi Orde Baru meliputi pengendalian hiperinflasi, penyesuaian anggaran belanja, pembukaan ekonomi untuk investasi asing, serta kerjasama dengan negara-negara maju untuk pembangunan jangka panjang. Rehabilitasi ekonomi difokuskan pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan skema fiskal seperti bantuan bersubsidi. Untuk mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi kapitalis dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang membuka jalan bagi investor asing untuk mengelola sumber daya hutan di Indonesia dengan konsesi investasi hingga 30 tahun, bahkan memungkinkan ekspansi bagi investor dengan komitmen tinggi.
3. Eksploitasi Hutan dan Dampaknya pada Lingkungan dan Masyarakat
Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1970 dan No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) memicu eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran. Kebijakan pembangunan kehutanan Orde Baru mengeksploitasi kayu untuk kepentingan negara dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Sistem eksploitasi ini memperburuk kualitas dan kuantitas sumber daya hutan, ditandai dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk kayu tropis Indonesia seperti kayu lapis, pulp, dan kertas. Instrumen pengelolaan hutan yang ada, seperti perusahaan HPH, industri pengolahan kayu, dan industri pulp dan paper, justru berkontribusi pada deforestasi. Model pertumbuhan ekonomi Orde Baru, meskipun menghasilkan devisa negara dan lapangan kerja, tidak memberikan kesejahteraan merata kepada rakyat dan mengakibatkan kerusakan hutan yang serius. Meningkatnya polutan mengancam lapisan ozon dan memperparah perubahan iklim akibat pemanasan global. Praktik pemanenan hasil hutan non-kayu yang tidak lestari dan konversi lahan hutan untuk sektor pertanian dan perkebunan semakin memperparah situasi. Akibatnya, Indonesia tidak hanya kehilangan tegakan kayu bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya masyarakat lokal yang terabaikan atau bahkan tergusur.
II.Dampak Deforestasi dan Tekanan Internasional
Laju deforestasi yang tinggi di era Soeharto memicu tekanan internasional. Konsumsi global produk kayu tropis dari Indonesia, termasuk kayu lapis dan pulp, meningkat pesat. Organisasi non-pemerintah (NGO) internasional mengkritik kebijakan kehutanan Orde Baru yang dianggap tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan lingkungan global. Ancaman boikot produk kayu Indonesia dari negara-negara maju (khususnya AS dan Eropa) mendorong desakan untuk kebijakan pengelolaan hutan yang lebih ketat dan berkelanjutan. Perubahan iklim dan pemanasan global menjadi dampak serius dari deforestasi ini, yang menimbulkan ancaman bagi keamanan lingkungan global.
1. Meningkatnya Konsumsi Global Produk Kayu Tropis Indonesia dan Dampaknya
Tingginya laju deforestasi di era Orde Baru di Indonesia berdampak pada meningkatnya permintaan global terhadap produk kayu tropis Indonesia. Indonesia menjadi penyedia utama produk kayu lapis, pulp (bubur kayu), dan kertas. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara deforestasi di Indonesia dengan konsumsi global produk kayu tersebut. Meningkatnya permintaan internasional terhadap produk-produk ini semakin memperburuk kondisi hutan di Indonesia karena memacu eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali. Sistem eksploitasi yang dilegalkan oleh pemerintah Orde Baru, yang melibatkan perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan), industri pengolahan kayu, dan industri pulp dan paper, menjadi pendorong utama deforestasi untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian hutan Indonesia dan menunjukkan kompleksitas masalah deforestasi yang melampaui batas wilayah Indonesia.
2. Tekanan Internasional dan Ancaman Boikot Produk Kayu Indonesia
Laju deforestasi yang tinggi di Indonesia pada masa Orde Baru mendapat perhatian dan tekanan dari masyarakat internasional. Negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, sebagai konsumen utama produk kayu Indonesia, mulai memandang aktivitas eksploitasi hutan Indonesia dengan citra negatif. Informasi dari NGO internasional yang mengungkap kerusakan jutaan hektar hutan akibat eksploitasi ini menyebabkan negara-negara maju mengancam untuk memboikot produk kayu Indonesia. Kebijakan pemerintah Orde Baru yang memprioritaskan sistem ekonomi-politik sebagai sumber pendapatan pembangunan negara, tanpa memperhatikan dampak lingkungan hidup global, menjadi sasaran kritik. Ancaman boikot ini memberikan tekanan signifikan kepada pemerintah Orde Baru untuk menerapkan kebijakan dan regulasi hukum yang lebih tegas terhadap pelaku HPH, memberikan sanksi kepada pelanggar, dan memperhatikan sistem pelestarian hutan. Tekanan internasional ini menunjukkan dampak global dari deforestasi Indonesia dan pentingnya kerjasama internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
3. Dampak Lingkungan Global dan Perubahan Iklim Akibat Deforestasi
Deforestasi di Indonesia pada era Orde Baru tidak hanya berdampak pada lingkungan lokal, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan global yang serius. Meningkatnya konsentrasi polutan menyebabkan ancaman kerusakan lapisan ozon dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan aset ekosistem hutan tropis menjadi sangat terancam karena degradasi hutan yang tidak terkendali. Penggunaan lahan hutan yang berubah dan hilangnya oksigen di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca yang memperbesar tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia. Deforestasi telah menjadi isu lingkungan global yang diperdebatkan di forum internasional karena dampaknya terhadap perubahan iklim. Meningkatnya laju deforestasi setiap tahunnya di era Soeharto menimbulkan kekhawatiran global terhadap perubahan iklim, dan menekankan urgensi pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.
III.Politik Lingkungan dan Dinamika Internasional
Isu deforestasi di Indonesia menjadi bagian dari politik lingkungan global. Konsep politik lingkungan menunjukkan keterkaitan antara ekonomi, politik, dan lingkungan dalam skala internasional. Pemerintah Orde Baru, yang bekerja sama dengan investor asing, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi hutan, mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional, termasuk peminjaman dana reboisasi, juga dibahas sebagai bagian dari dinamika ini. Peran LSM lingkungan dalam menyuarakan keprihatinan terhadap kerusakan hutan dan mendesak perubahan kebijakan juga menjadi fokus penting. Studi ini menganalisis hubungan kausal antara kebijakan, eksploitasi hutan, dan tekanan internasional yang berkaitan dengan perubahan iklim.
1. Konsep Politik Lingkungan dan Keterkaitannya dengan Deforestasi
Konsep politik lingkungan telah berkembang sejak akhir 1960-an dan awal 1970-an, mencakup aspek sosial, hukum, dan politik. Dalam konteks ini, lingkungan diartikan sebagai keadaan alam yang memprihatinkan dan memerlukan penanganan politik dari pemerintah. Isu deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan iklim menjadi perhatian utama negara berkembang dan internasional karena dampaknya terhadap pemanasan global. Kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya hutan, memiliki kontribusi biofisik pada peningkatan pemanasan global, yang berdampak negatif pada keamanan manusia. Untuk mengatasi ini, aktor-aktor politik, termasuk negara maju dan berkembang, lembaga internasional, dan masyarakat sipil, terlibat dalam penanggulangan kerusakan hutan. Isu deforestasi melibatkan aktor politik dari berbagai level, mulai dari negara hingga masyarakat sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan hutan produksi yang telah dieksploitasi pada masa Orde Baru belum optimal, sehingga kondisi lingkungan semakin memburuk. Dinamika politik menggambarkan relasi antara aktor dominan (pemilik kekuasaan) dan aktor yang terpinggirkan dalam eksploitasi hutan. Deforestasi di era Orde Baru menunjukkan kesalahan sistem pengelolaan hutan, dengan adanya korelasi antara deforestasi dan kelalaian HPH dalam mengimplementasikan konsep pembangunan kehutanan berbasis lingkungan, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat hutan.
2. Definisi Politik Lingkungan Global dan Peran Pemerintah Orde Baru
Porter dan Brown (1997:13) mendefinisikan politik lingkungan global sebagai persoalan lingkungan yang mengancam daya dukung alam (global commons) dan mempengaruhi kehidupan manusia di luar yuridiksi negara tertentu. Abe Ken-ichi mendefinisikannya sebagai analisis kritis terhadap masalah sumber daya alam dan kerusakannya yang dilakukan secara politik-ekonomi. Isu deforestasi tidak hanya membahas aspek teknis pengurangan emisi, tetapi juga kondisi ekonomi dan politik suatu negara, terutama negara penghasil emisi. Pengurangan emisi dapat mengganggu struktur perekonomian dan stabilitas politik. Pemerintah Orde Baru menjalin relasi dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dana reboisasi guna memperbaiki hutan yang rusak akibat eksploitasi, meskipun akhirnya tindakan ini memperburuk perekonomian Indonesia. Deforestasi menjadi unsur kerusakan lingkungan yang mempengaruhi keamanan global, membutuhkan dana rehabilitasi lahan hutan, dan kerjasama internasional. Kesimpulannya, konsep politik lingkungan pada era Orde Baru menunjukkan keterkaitan dalam dinamika politik internasional, dengan relasi aktor dominan (investor asing dan pemerintah) yang mengeksploitasi hutan untuk meningkatkan devisa negara, menghasilkan isu deforestasi yang menimbulkan rezim lingkungan dan politik lingkungan global.
3. Peran Hukum Internasional dan Pengabaian Pelestarian Hutan
Meskipun hukum lingkungan internasional melalui perjanjian internasional menekan pemerintah untuk melindungi lingkungan, pemerintah Orde Baru tetap mengabaikan pelestarian sumber daya hutan demi pembangunan ekonomi negara. Deforestasi mengancam kehidupan dan integritas budaya masyarakat yang bergantung pada hutan. Laju deforestasi pada masa Orde Baru dinilai paling serius karena berkaitan erat dengan sistem ekonomi-politik yang sentralistik. Pembangunan sumber daya hutan tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional, dengan Orde Baru mengekspor hasil eksploitasi hutan untuk pendapatan devisa negara. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (1967) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (1968) bertujuan meningkatkan pendapatan devisa untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi makro. Deforestasi merupakan isu perubahan lingkungan hidup dalam politik global, berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Kerusakan hutan pada era ini menjadi isu yang diperdebatkan di forum internasional, dan laju deforestasi yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran global terhadap perubahan iklim. Kebijakan otoriter Soeharto mengutamakan keuntungan perusahaan swasta dan negara, mengabaikan kehidupan dan nilai budaya masyarakat hutan.
IV.Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Sumber data meliputi literatur, artikel, internet, dan karya ilmiah dari perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan sumber daring lainnya. Analisis data melibatkan pengolahan data mentah, penyajian data visual, dan interpretasi teoritis.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Mayer dan Greenwood, pendekatan ini berfokus pada identifikasi sifat-sifat atau karakteristik yang membedakan suatu kelompok manusia, benda, atau peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif juga melibatkan proses konseptualisasi dan pembentukan skema klasifikasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail permasalahan deforestasi di Indonesia pada masa Orde Baru, berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.
2. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Data ini dikumpulkan melalui studi literatur, majalah, artikel, internet, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi perpustakaan pusat Universitas Gadah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Lab HI UMM, dan situs web yang terkait dengan deforestasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Penelitian ini berfokus pada analisis data yang sudah ada, bukan pada pengumpulan data primer melalui observasi lapangan atau wawancara langsung.
3. Metode Analisis Data
Proses analisis data meliputi pengolahan dan pengorganisasian data mentah menjadi bentuk yang sesuai untuk diolah menggunakan komputer. Data akan disajikan dalam berbagai bagan atau gambar untuk meringkas ciri-cirinya. Selanjutnya, interpretasi atau pemberian makna teoritis dilakukan terhadap hasil yang telah disajikan. Dengan demikian, analisis ini akan menghubungkan data yang telah dikumpulkan dengan kerangka teoritis yang relevan untuk menjelaskan isu deforestasi di Indonesia pada masa Orde Baru secara komprehensif. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dampak deforestasi dan tekanan internasional yang terkait.
