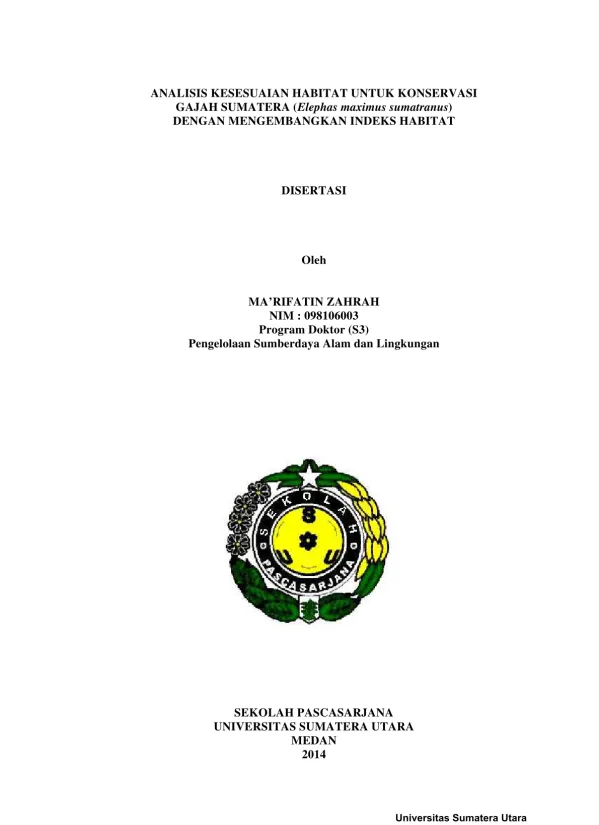
Analisis Kesesuaian Habitat untuk Konservasi Gajah Sumatera
Informasi dokumen
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 16.00 MB |
- konservasi gajah
- kesesuaian habitat
- pengelolaan sumberdaya alam
Ringkasan
I.Populasi dan Ancaman Gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus
Penelitian ini berfokus pada konservasi Gajah Sumatera, spesies yang terdaftar dalam IUCN Red List dan Appendix I CITES karena sebaran geografisnya yang sempit dan kepadatan populasi yang rendah. Populasi Gajah Sumatera diperkirakan menurun drastis, dari sekitar 2800-4800 ekor pada tahun 1985 menjadi 2400-2800 ekor pada tahun 2007. Ancaman utama meliputi penyempitan dan fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan liar. Habitat Gajah Sumatera terdiri dari berbagai tipe hutan, termasuk hutan rawa, hutan gambut, dan hutan hujan. Hilangnya habitat akibat konversi hutan untuk perkebunan dan pertanian menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup spesies ini.
1. Status Konservasi Gajah Sumatera dan Ancaman Kepunahan
Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah, terdaftar dalam IUCN Red List of Threatened Species dan Appendix I CITES. Status ini disebabkan oleh sebaran geografisnya yang terbatas dan kepadatan populasinya yang rendah. Salah satu upaya untuk mencegah kepunahan adalah dengan mempertahankan populasinya di alam liar (in situ). Data menunjukkan penurunan populasi yang signifikan, diperkirakan lebih dari 30% dalam kurun waktu 20 tahun, dari sekitar 2800-4800 individu (Blouch dan Haryanto serta Blouch dan Simbolon, 1985) menjadi 2400-2800 individu (Soehartono et al., 2007). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penyempitan dan fragmentasi habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan liar untuk diambil gadingnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan upaya konservasi yang intensif untuk menjamin kelangsungan hidup spesies ini dalam jangka panjang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian habitat di Cagar Alam Pinus Jantho untuk mendukung upaya konservasi ini.
2. Penyebaran dan Habitat Gajah Sumatera
Gajah Sumatera tersebar di tujuh provinsi di Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Meskipun penyebarannya cukup luas, populasi terkini belum dapat dipastikan secara keseluruhan karena kurangnya survei menyeluruh, kecuali di Provinsi Lampung (Hedges et al., 2005). Studi di Lampung menunjukkan kehilangan 9 dari 12 kantong populasi gajah sejak tahun 1980. Di Aceh, Gajah Sumatera tersebar di hampir semua kabupaten, dengan formasi pegunungan Bukit Barisan yang relatif baik dalam menghubungkan berbagai kantong habitat. Namun, pembukaan lahan hutan, terutama di dataran rendah, mengakibatkan konflik dengan manusia di wilayah perbatasan habitat gajah. Survei FFI (November 2007) bahkan menemukan kelompok gajah pada ketinggian 2.329 mdpl di Gunung Ulu Masen, Aceh, menunjukkan pemanfaatan koridor ketinggian untuk konektivitas habitat. Habitat Gajah Sumatera mencakup berbagai tipe hutan, seperti hutan rawa, hutan gambut, hutan hujan dataran rendah, dan hutan hujan pegunungan rendah (Haryanto, 1984). Kerusakan hutan yang luas akibat konversi lahan untuk perkebunan, transmigrasi, logging, dan perladangan liar menyebabkan fragmentasi habitat dan mengurangi populasi gajah menjadi kelompok-kelompok kecil (Santiapillai and Jackson, 1990). Hilangnya habitat, khususnya hutan dataran rendah (Holmes, 2001; FWI-GWF, 2001), yang diperkirakan mencapai 2 juta hektar per tahun, mengakibatkan pengurangan ruang gerak gajah dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia.
3. Reproduksi dan Perilaku Sosial Gajah Sumatera
Gajah Sumatera memiliki kemampuan reproduksi alami yang rendah, ditandai dengan masa kehamilan yang panjang (18-23 bulan), jarak antar kehamilan sekitar 4 tahun, masa menyusui selama 2 tahun, dan pengasuhan anak hingga usia 3 tahun (Sukumar, 2003; WWF). Nugrahanti (2003) mencatat interval melahirkan sekitar 4,5 tahun di Pusat Latihan Gajah Way Kambas, dengan umur betina melahirkan pertama kali antara 11-24 tahun. WWF menyebutkan kematangan reproduksi betina pada usia 8-10 tahun dan jantan pada usia 12-15 tahun. Usia hidup Gajah Asia bisa mencapai 60-70 tahun (Santiapillai and Jackson, 1990). Gajah Sumatera memiliki struktur sosial matriarkal, dipimpin oleh betina dewasa yang berpengaruh, dengan betina pemimpin di depan, diikuti oleh jantan remaja, betina lain, dan anak-anaknya (Suwelo dkk, 1983; Wittemyer et al., 2007). Jantan dewasa cenderung hidup soliter atau dalam kelompok kecil (Santiapillai and Jackson, 1990). Kebutuhan pakan gajah sangat tinggi, sekitar 150 kg tumbuhan per hari, dan mereka minum setidaknya sekali sehari. Aktivitas makan berlangsung di pagi, sore, dan malam hari, dengan istirahat siang hari untuk menghindari panas matahari karena kulitnya yang tipis (2-3 mm) (Leckagul and McNelly, 1977; Eltringham, 1982; WWF). Wilayah jelajah Gajah Sumatera cukup luas, diperkirakan 680 hektar per ekor (Santiapillai, 1987) atau 370-830 hektar (Olivier, 1978).
II.Cagar Alam Pinus Jantho sebagai Kawasan Pengelolaan Gajah
Cagar Alam Pinus Jantho di Aceh Besar, bagian dari Ekosistem Ulu Masen, diidentifikasi sebagai kawasan potensial untuk Kawasan Pengelolaan Gajah. Luas Cagar Alam Pinus Jantho adalah 16.640 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian kawasan ini sebagai Managed Elephant Range dengan mengembangkan indeks habitat berdasarkan komponen fisiografi, biologis, dan sosial. Studi ini melibatkan survei lapangan untuk menilai potensi habitat, termasuk produksi pakan gajah, keanekaragaman jenis tumbuhan pakan, sumber air, dan salt licks. Estimasi kepadatan populasi dilakukan menggunakan metode dung count. Data sosial dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner.
1. Cagar Alam Pinus Jantho Lokasi dan Karakteristik
Penelitian ini meneliti Cagar Alam Pinus Jantho di Aceh Besar sebagai potensial Kawasan Pengelolaan Gajah. Secara geografis, Cagar Alam Pinus Jantho terletak pada koordinat 5°6' LU – 5°16.2' LU dan 95°37.2' BT – 95°45' BT, dengan luas 16.640 hektar. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 186/Kpts-II/1984 tanggal 4 Oktober 1984. Kawasan ini penting karena merupakan perwakilan hutan alam Pinus merkusii strain Aceh, serta menjadi habitat bagi satwa dilindungi seperti Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera. Cagar Alam Pinus Jantho juga merupakan hulu Sungai Krueng Aceh dan daerah tangkapan air yang vital bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh, menyediakan sumber air penting bagi PDAM Aceh Besar dan Kota Banda Aceh (BKSDA, 2007). Vegetasi di Cagar Alam Pinus Jantho beragam, termasuk hutan pinus alam, padang rumput yang luas, dan hutan alam dataran rendah dengan berbagai jenis flora seperti Mampre (Dillenia sp.), Jambu air (Eugenia aquaea), Ara (Ficus sp.), Damar (Agathis dammara), dan berbagai jenis lainnya. Keanekaragaman fauna juga tinggi, meliputi Siamang (Symphalagus syndactylus), Kambing Hutan (Capricornis sumatraensis sumatraensis), Beruang madu (Helarctos malayanus), dan Trenggiling (Manis javanica).
2. Tujuan dan Metodologi Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan kesesuaian Cagar Alam Pinus Jantho sebagai Managed Elephant Range. Untuk mencapai tujuan ini, dikembangkan indeks habitat yang mempertimbangkan komponen fisiografi, biologis, dan sosial. Survei lapangan dilakukan untuk menilai potensi habitat dengan mengukur beberapa parameter kunci. Parameter biologis meliputi produksi pakan gajah, keanekaragaman jenis tumbuhan pakan, keberadaan sumber air, dan salt licks. Estimasi kepadatan populasi gajah dilakukan dengan pendekatan dung count. Sementara itu, data kondisi sosial masyarakat sekitar hutan dikumpulkan melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui analisis statistika dan spasial menggunakan aplikasi GIS dan perangkat lunak statistika. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian kawasan sebagai habitat gajah dan Kawasan Pengelolaan Gajah.
3. Hasil dan Analisis Kesesuaian Habitat
Hasil analisis menunjukkan potensi habitat gajah di Cagar Alam Pinus Jantho sangat mendukung dan sangat sesuai sebagai Kawasan Pengelolaan Gajah, dengan nilai indeks awal sebesar 89,32. Namun, nilai indeks ini turun menjadi 73 setelah memasukkan parameter desa sekitar hutan sebagai komponen indeks. Berdasarkan klasifikasi kesesuaian, 9117,91 Ha (54,24%) kawasan dikategorikan sebagai ruang habitat yang sangat sesuai untuk gajah, sementara 6096,94 Ha (36,26%) dikategorikan sebagai ruang habitat yang sesuai. Wilayah yang sangat sesuai dan sesuai didominasi oleh vegetasi hutan sekunder, lahan rerumputan, dan semak belukar dengan karakteristik tertentu seperti tutupan tajuk jarang sampai sedang, dekat dengan sumber air, ketinggian kurang dari 800 m dpl, dan kelerengan datar sampai landai. Analisis overlay peta menunjukkan bahwa 65% jejak gajah ditemukan di area yang sangat sesuai, dan 35% di area yang sesuai. Area yang kurang sesuai dan tidak sesuai tidak ditemukan jejak gajah.
III.Analisis Kesesuaian Habitat Gajah Sumatera di Cagar Alam Pinus Jantho
Hasil analisis menunjukkan bahwa Cagar Alam Pinus Jantho memiliki potensi yang sangat baik sebagai habitat Gajah Sumatera. Nilai indeks habitat awal mencapai 89,32, namun turun menjadi 73 setelah mempertimbangkan faktor sosial dari desa-desa sekitar hutan. Sebanyak 9117,91 Ha (54,24%) kawasan dikategorikan sebagai ruang yang sangat sesuai untuk Gajah Sumatera, sementara 6096,94 Ha (36,26%) dikategorikan sebagai ruang yang sesuai. Ruang yang sangat sesuai dan sesuai didominasi oleh vegetasi hutan sekunder, lahan rerumputan, dan semak belukar dengan tutupan tajuk jarang hingga sedang, dekat dengan sumber air, ketinggian < 800 m dpl, dan kelerengan datar hingga landai. Peta overlay menunjukkan 65% jejak gajah ditemukan di area yang sangat sesuai dan 35% di area yang sesuai.
1. Pengembangan Indeks Kesesuaian Habitat
Penelitian ini mengembangkan indeks kesesuaian habitat untuk menentukan seberapa cocok Cagar Alam Pinus Jantho sebagai habitat Gajah Sumatera. Indeks ini menggabungkan komponen fisiografi (topografi, ketinggian, kemiringan), biologis (ketersediaan pakan, sumber air, salt licks, keanekaragaman tumbuhan pakan), dan sosial (pengaruh desa sekitar hutan). Proses pengembangan indeks melibatkan studi literatur, penyebaran kuesioner kepada para ahli, survei lapangan untuk pengumpulan data, dan penilaian parameter habitat berdasarkan preferensi Gajah Sumatera. Model kesesuaian habitat dibangun melalui agregasi beberapa sub-indeks variabel habitat (Ott, 1978), menggunakan persamaan polynomial karena memberikan koefisien determinasi (R²) yang lebih tinggi dibandingkan persamaan linear, terutama untuk indikator komoditi yang ditanam di sekitar kawasan.
2. Analisis Spasial dan Klasifikasi Kesesuaian
Analisis spasial dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan memasukkan data spasial berupa peta dan data lapangan (lokasi kubangan, jejak/kotoran gajah, sebaran vegetasi pakan, salt licks) yang direkam menggunakan GPS. Data diolah menggunakan software ArcView 3.3 dan Microsoft Excel. Analisis ini menghasilkan informasi mengenai topografi, luasan tipe tutupan lahan, tingkat fragmentasi habitat, sebaran sumber daya, dan sebaran gajah. Data keberadaan koridor diperoleh dari data FFI. Berdasarkan klasifikasi kesesuaian habitat yang dihasilkan, didapatkan nilai indeks awal sebesar 89,32, menunjukkan potensi habitat yang sangat tinggi. Namun, nilai indeks turun menjadi 73 setelah mempertimbangkan parameter desa sekitar hutan. Klasifikasi kesesuaian menunjukkan bahwa 9117,91 Ha (54,24%) kawasan sangat sesuai untuk habitat gajah, dan 6096,94 Ha (36,26%) sesuai. Vegetasi hutan sekunder, lahan rerumputan, dan semak belukar dengan karakteristik tertentu (tutupan tajuk jarang-sedang, dekat sumber air, ketinggian < 800 m dpl, kelerengan datar-landai) mendominasi area yang sangat sesuai dan sesuai. Sebaliknya, hutan primer dengan tajuk rapat, ketinggian > 800 m dpl, dan kelerengan terjal dikategorikan sebagai ruang yang kurang sesuai atau tidak sesuai.
3. Interpretasi Peta dan Kesimpulan
Berdasarkan overlay peta, 65% jejak gajah ditemukan di area yang sangat sesuai dan 35% di area yang sesuai, sementara area kurang sesuai dan tidak sesuai tidak ditemukan jejak gajah. Secara keseluruhan, sekitar 90,5% dari total luas Cagar Alam Pinus Jantho dikategorikan sebagai ruang yang sangat sesuai dan sesuai untuk mendukung kehidupan gajah. Kesimpulannya, Cagar Alam Pinus Jantho memiliki potensi yang sangat besar sebagai habitat Gajah Sumatera dan layak untuk dikelola sebagai Kawasan Pengelolaan Gajah. Namun, faktor sosial dari masyarakat sekitar hutan perlu dipertimbangkan secara serius dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan untuk meminimalisir konflik dan memastikan keberlanjutan konservasi Gajah Sumatera. Analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi kesesuaian habitat, seperti aktivitas manusia di sekitar kawasan, penting untuk strategi pengelolaan jangka panjang.
IV.Faktor Faktor yang Mempengaruhi Habitat Gajah Sumatera
Studi ini juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian habitat, termasuk ketersediaan pakan (dengan analisis keanekaragaman jenis tumbuhan pakan), ketersediaan air, dan kondisi fisiografi. Pentingnya koridor habitat untuk konektivitas antar populasi Gajah Sumatera juga dibahas. Konflik antara manusia dan gajah, khususnya terkait penggunaan lahan pertanian dan perkebunan di sekitar Cagar Alam Pinus Jantho, juga dipertimbangkan sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan konservasi Gajah Sumatera.
1. Ketersediaan Pakan Gajah Sumatera
Ketersediaan pakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesesuaian habitat Gajah Sumatera. Penelitian ini mencatat berbagai jenis tumbuhan pakan yang dikonsumsi Gajah Sumatera, dengan variasi jenis dan ketersediaan yang berbeda di setiap tipe vegetasi. Zahrah (2002) menemukan 55 jenis tumbuhan pakan dari 20 suku di hutan Sekundur, Aras Napal (Sumatera Utara), dan Serbajadi (Aceh Timur), didominasi suku Poaceae, Arecaceae, Mimosaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae, Palmae, Myrtaceae, dan Zingiberaceae. Ketersediaan pakan bervariasi; hutan primer dan sekunder tua didominasi palem dan rotan, hutan sekunder muda didominasi herba, dan semak belukar didominasi rumput. Seblat Elephant Conservation Center mencatat setidaknya 273 jenis tumbuhan pakan dari 69 suku, dengan Moraceae, Arecaceae, Fabaceae, Poaceae, dan Euphorbiaceae sebagai yang paling sering dikonsumsi. Gajah Sumatera lebih menyukai daun-daunan (browsed) daripada rumput (grazed), terutama di musim hujan (Sitompul, 2011). Studi di Nepal menunjukkan dominasi daun-daunan (66%), rumput (lebih dari 25%), dan herba (9%) dalam pakan Gajah Asia (Steinheim et al., 2005). Jenis-jenis rumput yang disukai gajah di lokasi penelitian adalah Saccharum spontaneum dan Echinochloa crus-galli, yang melimpah di lahan rerumputan.
2. Ketersediaan Air dan Kondisi Fisiografi
Ketersediaan air merupakan faktor vital bagi Gajah Sumatera, dibutuhkan tidak hanya untuk minum (20-50 liter/hari, WWF) tetapi juga untuk mandi, berendam, dan berkubang, serta interaksi sosial. Meskipun Eltringham (1982) mencatat Gajah Afrika kurang bergantung pada air, bagi Gajah Sumatera, keberadaan sumber air permukaan (sungai, alur, kolam) sangat penting dan memengaruhi persebaran mereka. Kondisi fisiografi habitat, meliputi ketinggian, kemiringan lereng, dan tutupan tajuk vegetasi, juga berpengaruh. Gajah Sumatera lebih menyukai area dengan ketinggian < 800 m dpl dan kelerengan datar sampai landai, dengan tutupan tajuk jarang sampai sedang untuk menghindari sengatan matahari langsung. Mereka mencari tempat teduh untuk beristirahat pada siang hari dan sering tidur berdiri di malam hari (WWF). Kebutuhan area jelajah yang luas, diperkirakan 680 hektar/ekor (Santiapillai, 1987) atau 370-830 hektar (Oliver, 1978), juga memengaruhi kesesuaian habitat.
3. Pengaruh Faktor Sosial dan Konektivitas Habitat
Faktor sosial masyarakat sekitar hutan juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas dan kuantitas habitat Gajah Sumatera. Jumlah penduduk, luas dan pemanfaatan lahan garapan masyarakat, serta jenis komoditi pertanian yang ditanam merupakan parameter penting dalam indeks kesesuaian habitat. Konflik manusia-gajah sering terjadi di daerah dengan penggunaan lahan pertanian yang berdekatan dengan habitat gajah, khususnya penanaman tanaman yang disukai gajah seperti padi, jagung, sawit, kakao, dan ubi (Purastuti, 2010). Konektivitas habitat, atau keberadaan koridor, sangat penting untuk memfasilitasi penyebaran Gajah Sumatera, mengurangi risiko kepunahan akibat fragmentasi habitat, dan memastikan aliran genetik antar populasi (Good, 1998). Studi ini menganalisis keberadaan koridor yang menghubungkan Cagar Alam Pinus Jantho dengan area lain, guna menjamin keberlangsungan populasi minimum yang dibutuhkan (minimum viable population).
