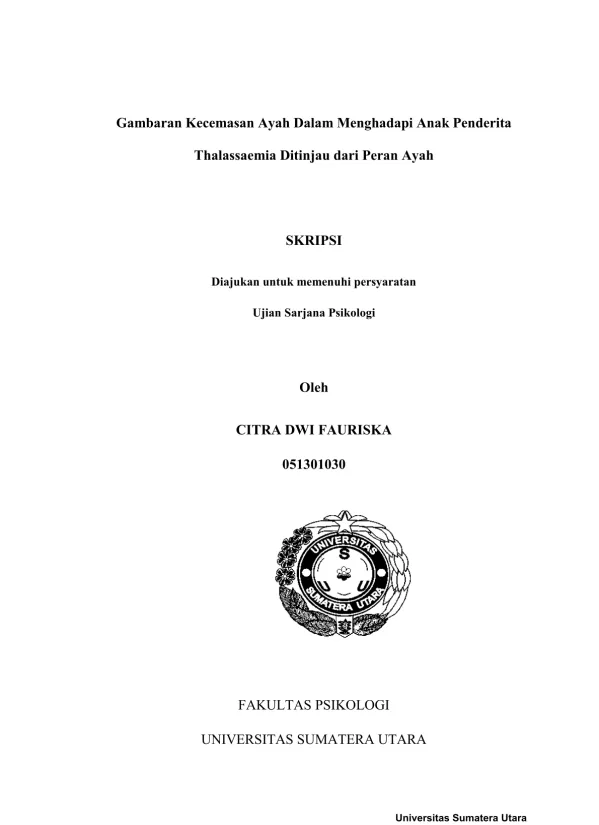
Kecemasan Ayah dalam Menghadapi Anak Penderita Thalassaemia
Informasi dokumen
| Penulis | Citra Dwi Fauriska |
| instructor | Elvi Andriani Yusuf, M.Psi |
| Sekolah | Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara |
| Jurusan | Psikologi |
| Tahun terbit | 2011/2012 |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 1.92 MB |
- Kecemasan Ayah
- Thalassaemia
- Peran Keluarga
Ringkasan
I.Latar Belakang Masalah Background of the Problem
Penelitian ini meneliti kecemasan ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia. Thalassaemia, suatu penyakit kelainan darah genetik, memberikan beban berat secara fisik dan psikis bagi keluarga, terutama ayah. Di Indonesia, terdapat lebih dari 20.000 penderita Thalassaemia dari total 200 juta penduduk (Kompas, 2009). Biaya pengobatan yang tinggi dan sifat penyakit yang kronis menambah kecemasan orang tua. Penelitian ini penting karena peran ayah dalam keluarga, khususnya dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia, seringkali kurang mendapat perhatian.
1. Kompleksitas Kesehatan Modern dan Penyakit Thalassaemia
Bagian ini memulai dengan menekankan kompleksitas masalah kesehatan di zaman modern, di mana berbagai faktor lingkungan dan kondisi kehidupan meningkatkan risiko penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Orang tua tentu mendambakan anak yang sehat, baik fisik maupun psikis. Namun, realitanya tidak semua anak terlahir sehat. Thalassaemia, sebuah penyakit kelainan darah genetik (Kusumawardani, 2010), diangkat sebagai contoh penyakit serius yang dapat dialami anak. Disebutkan bahwa Thalassaemia merupakan kelainan genetik yang umum, bahkan banyak dialami oleh orang Amerika keturunan Italia (Tim Penulis Fakultas Kedokteran UI, 1985). Data dari National Academy of Sciences menunjukkan lebih dari 100.000 bayi di dunia lahir dengan kondisi Thalassaemia yang berat (Cooley’s Anemia Foundation, 2006), sementara di Indonesia, jumlah penderita mencapai 20.000 orang dari total populasi 200 juta (Kompas, 2009). Thalassaemia ditandai dengan kekurangan hemoglobin, sehingga membutuhkan transfusi darah rutin. Hal ini menjadi latar belakang penting penelitian tentang kecemasan orang tua, khususnya ayah, dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia.
2. Beban Orang Tua dan Peran Ayah yang Kurang Tersorot
Orang tua yang memiliki anak penderita Thalassaemia menanggung beban berat, baik secara moral maupun material (Tamam, 2009). Selain memonitor perkembangan anak, biaya transfusi darah yang mahal, mencapai jutaan rupiah per bulan, menjadi tantangan besar. Lebih lagi, Thalassaemia merupakan penyakit seumur hidup tanpa obat penyembuh, hanya perawatan suportif (Lanni, 2008). Kecemasan orang tua, terutama saat anak sakit, merupakan reaksi emosional yang wajar, bahkan untuk penyakit ringan sekalipun (Hawari, 2000; Wahidiyat, 2009). Meskipun ayah memiliki tanggung jawab besar dalam keluarga, perannya seringkali kurang mendapat sorotan (Dagun, 2002; Marlina, 2009). Pandangan tradisional yang menempatkan ayah hanya sebagai pencari nafkah tanpa keterlibatan langsung dalam pengasuhan anak seringkali dijumpai. Hal ini menjadi titik krusial yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu bagaimana kecemasan ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia terkait dengan peran dan tanggung jawabnya yang seringkali terabaikan.
3. Kecemasan Orang Tua di Rumah Sakit dan Peran Ayah yang Kuat Namun Tersembunyi
Orang tua mengalami kecemasan saat anak dirawat di rumah sakit, terutama karena kekhawatiran terhadap proses medis, kesulitan menjelaskan penyakit kepada anak, dan menghadapi rasa sakit anak yang mungkin sulit diungkapkan (Sarafino, 2006). Ayah, yang sering digambarkan sebagai sosok kuat dan tegar (Friedman, 1998), mungkin menyembunyikan kecemasannya. Konsep fathering atau peran ayah dalam pengasuhan dan membimbing anak menuju kemandirian (baik fisik maupun psikologis) juga dibahas. Studi kasus menunjukkan bagaimana ayah dapat mendampingi anak dalam perawatan medis dan mengatasi emosi yang timbul. Namun, situasi darurat atau ketidakhadiran istri dapat meningkatkan kebingungan ayah (Sutedja, 2009). Perbedaan reaksi ayah terhadap anak laki-laki dan perempuan juga disinggung; ayah lebih protektif terhadap anak perempuan (Dagun, 2002). Keseluruhan bagian ini membangun konteks pentingnya memahami dan menganalisis kecemasan yang dialami ayah secara spesifik, mengingat peran dan dinamika kehidupannya yang unik.
II.Peran Ayah The Role of the Father
Penelitian ini mengeksplorasi peran ayah dalam keluarga yang memiliki anak penderita Thalassaemia. Peran ayah meliputi pencari nafkah, pemberi rasa aman, pendidik, dan ikut serta dalam perawatan anak. Studi ini akan menganalisis bagaimana peran-peran ini terpengaruh dan berinteraksi dengan kecemasan ayah di tengah tantangan merawat anak dengan Thalassaemia.
1. Pengertian Peran Ayah dalam Keluarga
Bagian ini mendefinisikan peran ayah dalam keluarga. Pasaribu & Pribadi (1981) menjabarkan tugas orang tua, termasuk pendidikan, pengasuhan, dan nafkah, yang secara implisit membagi peran antara ibu dan ayah. Simanjuntak dan Pasaribu (1981) menambahkan peran ayah dalam pengelolaan rumah tangga sebagai kepala keluarga. Lebih lanjut, Gunarsa (1995) menjelaskan peran ayah sebagai pendidik, khususnya dalam hal rasionalitas, dan sebagai tokoh identifikasi bagi anak, membantu pembentukan super ego yang ideal. Keberadaan ayah yang berpribadi kuat sangat penting dalam membentuk kepribadian anak yang baik. Kesejahteraan ekonomi keluarga sangat bergantung pada penghasilan ayah, dan ayah juga berperan sebagai suami yang penuh pengertian dan pemberi rasa aman bagi istri, menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga. Kehadiran ayah yang suportif sangat penting bagi keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Peran-peran ayah ini menjadi dasar pemahaman bagaimana peran tersebut berdampak dan berinteraksi dengan kecemasan ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia.
2. Peran Ayah dalam Menghadapi Anak Penderita Thalassaemia
Bagian ini membahas secara spesifik bagaimana peran ayah berkaitan dengan kondisi memiliki anak penderita Thalassaemia. Rizkiani (2009) menjelaskan Thalassaemia sebagai penyakit dimana sel darah merah mudah rusak, menyebabkan anemia. Thalassaemia beta, yang umum di Indonesia, merupakan penyakit hemolitik seumur hidup (IDAI, 2004), menimbulkan masalah medis dan sosial. Diagnosa awal Thalassaemia sulit, meski teknologi molekuler dapat membantu identifikasi mutasi genetik. Dampak Thalassaemia mayor terhadap perkembangan anak meliputi masalah fisik (lemah, lesu, pucat) dan psikis (depresi, kecemasan) (Eleftheriou, 2003), serta potensi putus sekolah dan isolasi sosial. Gandhi (dalam Aceh Forum, 2009) menambahkan bahwa anak penderita Thalassaemia memiliki tubuh lemah, mudah lelah, dan butuh pembatasan makanan. Diagnosis Thalassaemia dapat menimbulkan stres pada hubungan pasangan dan keluarga. Meskipun demikian, penyakit ini juga bisa memperkuat ikatan keluarga. Namun, ayah mungkin memfokuskan perhatian pada anak yang sakit, mengabaikan anggota keluarga lain (Eleftheriou, 2003). Ayah seringkali kurang mendapat dukungan dalam mengasuh anak sakit (Shonkoff, dalam Cunningham, 1996), namun kehadirannya penting bagi ketabahan anak (Sutedja, 2009). Situasi darurat dapat meningkatkan kebingungan ayah, terutama jika istri tidak ada (Sutedja, 2009).
III.Dampak Thalassaemia Mayor bagi Perkembangan Anak Impact of Thalassaemia Major on Child Development
Thalassaemia mayor berdampak signifikan pada perkembangan anak, baik fisik (lemas, pucat, keterbatasan aktivitas) maupun psikis (depresi, kecemasan, isolasi). Anak-anak dengan Thalassaemia seringkali membutuhkan transfusi darah rutin, yang menimbulkan beban finansial dan emosional bagi keluarga. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana dampak tersebut berkontribusi pada kecemasan ayah.
1. Dampak Fisik Thalassaemia Mayor
Thalassaemia mayor menimbulkan berbagai dampak fisik pada anak. Eleftheriou (2003) menjelaskan penderita Thalassaemia mengalami masalah fisik seperti kelemahan, lesu, mudah lelah, serta pembatasan makanan tertentu karena masalah pencernaan dan sesak napas. Gejala-gejala ini dapat diamati sejak anak berusia satu hingga dua tahun, ditandai dengan pucat, pusing, kurang nafsu makan, dan pertumbuhan yang lambat (Cooley’s Anemia Foundation, 2006). Anak juga sering mengalami jaundice (warna kuning pada mata dan kulit). Gandhi (dalam Aceh Forum, 2009) menambahkan ciri-ciri fisik lainnya seperti tubuh lemah, mudah lelah, pucat, dan kurang bersemangat, yang biasanya sudah terlihat sejak usia muda (kurang dari 2 tahun). Aktivitas fisik anak juga harus dibatasi karena dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Kondisi fisik yang lemah ini secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari anak, membatasi aktivitas bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya, dan berpotensi menyebabkan putus sekolah.
2. Dampak Psikis dan Psikososial Thalassaemia Mayor
Selain dampak fisik, Thalassaemia mayor juga berdampak signifikan pada aspek psikis dan psikososial anak. Eleftheriou (2003) mencatat dampak psikis berupa depresi, kegelisahan, kecemasan, dan berbagai ketakutan, termasuk takut akan kematian dan rasa sakit. Anak juga dapat mengalami perasaan terisolasi, kehilangan kepercayaan, ketidakberdayaan, dan kesedihan. Dampak psikososial meliputi peningkatan risiko putus sekolah karena kesulitan mengikuti aktivitas fisik di lingkungan sekolah, kesulitan bersosialisasi dan membentuk pertemanan, serta perasaan terisolasi. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi anak secara individu, tetapi juga berdampak pada seluruh keluarga, terutama orang tua yang harus menghadapi tantangan fisik, emosional, dan mental dalam mengasuh anak penderita Thalassaemia. Kondisi ini sangat relevan dengan penelitian tentang kecemasan ayah dalam konteks ini.
3. Kriteria Diagnostik Thalassaemia Mayor
Diagnosis Thalassaemia mayor ditegakkan melalui anamnesis (riwayat penyakit), pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Cooley’s Anemia Foundation (2006) menyebutkan bahwa meskipun bayi terlihat sehat saat lahir, setelah satu hingga dua tahun, gejala-gejala seperti pucat, pusing, kurang nafsu makan, dan pertumbuhan yang lambat akan muncul. Warna kuning pada kulit dan mata (jaundice) juga merupakan gejala khas. Anak yang menderita Thalassaemia mayor dapat mewariskan penyakit tersebut pada keturunannya, bahkan jika pasangannya bukan pembawa sifat (carrier) penyakit tersebut. Pemahaman tentang kriteria diagnostik ini sangat penting karena diagnosis awal yang tepat sangat krusial dalam memberikan penanganan yang tepat dan mengurangi dampak negatif penyakit Thalassaemia pada perkembangan anak. Informasi ini penting untuk dipahami dalam konteks penelitian tentang kecemasan orang tua, terutama ayah, yang berhadapan dengan penyakit ini.
IV.Metodologi Penelitian Research Methodology
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap ayah yang memiliki anak penderita Thalassaemia. Wawancara difokuskan pada gambaran kecemasan ayah, penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan peran ayah dalam menghadapi situasi tersebut. Data dianalisis menggunakan teknik coding untuk mengidentifikasi tema dan pola yang relevan dengan kecemasan ayah dan Thalassaemia.
1. Pendekatan Kualitatif Deskriptif
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam kecemasan ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia. Pilihan ini didasarkan pada argumen Poerwandari (2007) bahwa pendekatan kualitatif paling tepat untuk memahami kompleksitas manusia sebagai makhluk subjektif. Kecemasan, sebagai pengalaman subjektif, membutuhkan pendekatan yang mampu menggali pemahaman yang luas dan mendalam. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kecemasan ayah dalam konteks tersebut. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang diteliti.
2. Teknik Pengumpulan Data Wawancara Mendalam
Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam dengan para ayah yang memiliki anak penderita Thalassaemia. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara umum, yang memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam menggali informasi tanpa terikat pada urutan pertanyaan yang ketat. Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan untuk memastikan isu-isu penting terkait kecemasan ayah, penyebabnya, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan peran ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia tercakup dalam wawancara. Purwandari (2001) menekankan pentingnya pedoman wawancara sebagai pengingat aspek-aspek yang perlu dibahas dan sebagai daftar pengecekan (checklist) untuk memastikan semua aspek relevan telah dibahas. Wawancara mendalam dipilih karena dianggap mampu menggali informasi yang kaya dan bermakna dari perspektif para ayah.
3. Analisis Data Coding
Setelah pengumpulan data melalui wawancara, tahap selanjutnya adalah analisis data menggunakan teknik coding. Coding dilakukan untuk mengorganisir dan menyistematiskan data secara lengkap dan detail. Proses ini bertujuan untuk mengungkap gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti dan menemukan makna dari data yang terkumpul. Semua peneliti kualitatif menganggap coding sebagai tahap penting, meskipun prosedur yang digunakan mungkin berbeda. Peneliti memiliki kebebasan memilih cara coding yang paling efektif untuk data yang diperolehnya. Proses coding ini akan membantu mengidentifikasi tema dan pola yang relevan dengan kecemasan ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena tersebut.
V.Hasil Penelitian Research Findings
Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun mengalami kecemasan yang signifikan, kehadiran kelompok dukungan sesama orang tua anak penderita Thalassaemia membantu meringankan beban. Kecemasan ayah muncul dari berbagai sumber, termasuk beban finansial (meski sebagian ditanggung Jamkesmas), ketakutan akan kondisi kesehatan anak yang memburuk, dan proses pengobatan yang rumit. Peran ayah bervariasi, dengan beberapa ayah sangat terlibat dalam perawatan, sementara yang lain terhambat oleh tuntutan pekerjaan. Penelitian ini dilakukan di Medan, Sumatera Utara, dengan melibatkan beberapa responden ayah dari pasien Thalassaemia di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Methodist Medan.
1. Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kecemasan Ayah
Temuan utama menunjukkan adanya pengaruh positif dari dukungan sosial terhadap kecemasan ayah yang memiliki anak penderita Thalassaemia. Meskipun semua responden merasakan kecemasan dan ketakutan, kehadiran kelompok dukungan sesama orang tua penderita Thalassaemia membantu meringankan beban. Responden III bahkan menyatakan bahwa ketakutan dan kecemasannya berkurang setelah mengetahui banyak orang tua lain yang mengalami hal serupa, bahkan dengan kondisi anak yang lebih berat. Temuan ini menyoroti pentingnya peran dukungan sosial dalam mengurangi dampak psikologis penyakit kronis pada keluarga. Dukungan sosial memberikan rasa tidak sendirian dan membantu orang tua untuk lebih mudah menghadapi tantangan dalam perawatan anak.
2. Sumber Sumber Kecemasan Ayah
Kecemasan ayah terhadap anak penderita Thalassaemia berasal dari beberapa sumber. Aspek keuangan, meskipun sebagian besar biaya perawatan ditanggung oleh program Jamkesmas, tetap menjadi sumber kecemasan. Ketakutan akan penurunan drastis kondisi kesehatan anak yang tiba-tiba juga menjadi perhatian besar. Kesulitan dan prosedur perawatan dan pengobatan yang rumit menambah beban psikologis. Kehabisan stok darah di PMI, yang mengharuskan pembelian darah dengan biaya sendiri, juga menjadi kekhawatiran utama. Dalam beberapa kasus, ayah harus mencari donor pengganti, yang menambah kompleksitas situasi. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kecemasan ayah tidak hanya terkait dengan aspek medis, tetapi juga aspek sosial ekonomi dan sistem layanan kesehatan.
3. Peran Ayah dalam Perawatan dan Pengobatan
Peran ayah dalam perawatan dan pengobatan anak penderita Thalassaemia bervariasi. Peran ayah meliputi pencari nafkah, pemberi rasa aman dan perlindungan, dan pemberi perhatian dalam pendidikan. Dalam konteks perawatan, keterlibatan ayah bervariasi. Responden III, misalnya, kurang terlibat langsung karena bekerja seharian sebagai kurir, sementara perawatan anak sering dijadwalkan di pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan ekonomi dan keterbatasan waktu dapat membatasi keterlibatan ayah dalam perawatan anak yang sakit. Temuan ini menunjukkan kompleksitas peran ayah dalam keluarga yang memiliki anggota keluarga penderita Thalassaemia dan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial ekonomi dalam memahami kecemasan dan perilaku ayah.
VI.Kesimpulan dan Saran Conclusion and Suggestions
Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dan pemahaman terhadap kecemasan ayah yang memiliki anak penderita Thalassaemia. Temuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang tepat sasaran untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan anak penderita Thalassaemia di Indonesia. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji peran faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecemasan ayah, serta mengeksplorasi strategi dukungan yang efektif.
1. Kesimpulan Utama Kecemasan Ayah dan Dukungan Sosial
Kesimpulan utama penelitian ini adalah kecemasan ayah dalam menghadapi anak penderita Thalassaemia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun kecemasan tersebut signifikan, kehadiran kelompok dukungan sesama orang tua penderita Thalassaemia memberikan dampak positif dalam meringankan beban psikologis. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan sosial sebagai strategi dalam membantu ayah mengatasi kecemasan mereka. Kecemasan tersebut muncul dari berbagai sumber, termasuk kekhawatiran finansial, risiko penurunan kondisi kesehatan anak yang mendadak, serta kompleksitas prosedur pengobatan. Penting untuk diingat bahwa walaupun program Jamkesmas membantu meringankan beban finansial, kesulitan seperti kekurangan stok darah di PMI tetap menjadi sumber kecemasan.
2. Saran untuk Intervensi dan Penelitian Lanjutan
Penelitian ini menyarankan pengembangan intervensi yang tepat sasaran untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga yang memiliki anak penderita Thalassaemia. Intervensi tersebut dapat fokus pada penyediaan dukungan sosial yang lebih efektif, peningkatan akses informasi tentang Thalassaemia, dan penyederhanaan prosedur pengobatan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang memengaruhi kecemasan ayah, seperti tingkat pendidikan, dukungan dari pasangan, dan karakteristik kepribadian. Strategi dukungan yang lebih spesifik dan efektif juga perlu dieksplorasi, mempertimbangkan konteks budaya dan sosial ekonomi keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan program-program pendukung yang lebih komprehensif bagi keluarga dengan anak penderita Thalassaemia di Indonesia.
