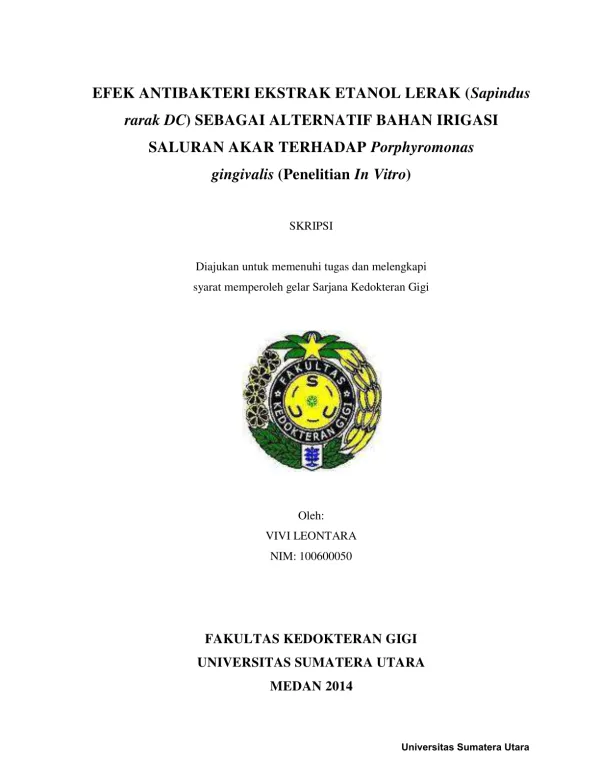
Efek Antibakteri Ekstrak Etanol Lerak terhadap Porphyromonas gingivalis
Informasi dokumen
| Penulis | Vivi Leontara |
| Sekolah | Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara |
| Jurusan | Kedokteran Gigi |
| Tempat | Medan |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 5.77 MB |
- antibakteri
- ekstrak etanol
- Porphyromonas gingivalis
Ringkasan
I.Latar Belakang Infeksi Saluran Akar dan Porphyromonas gingivalis
Penelitian ini berfokus pada infeksi endodontik primer, khususnya peran Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), bakteri anaerob gram-negatif yang membentuk biofilm dalam saluran akar yang terinfeksi. P. gingivalis dikenal memiliki virulensi tinggi dan sulit dieliminasi, sering dikaitkan dengan abses periapikal. Penelitian sebelumnya menunjukkan prevalensi P. gingivalis yang signifikan (28%-43,3%) pada infeksi endodontik primer. Oleh karena itu, pencarian alternatif bahan irigasi saluran akar yang efektif terhadap P. gingivalis sangat penting.
1. Peranan Bakteri dalam Penyakit Pulpa dan Periapikal
Bagian ini menjelaskan peran utama bakteri dalam perkembangan penyakit pulpa dan periapikal. Disebutkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh infeksi oportunis patogen bakteri yang menyerang jaringan pulpa dan periapikal. Infeksi saluran akar bersifat polimikrobial, melibatkan berbagai spesies bakteri yang berinteraksi erat satu sama lain. Bakteri-bakteri ini membentuk biofilm, suatu komunitas terintegrasi secara metabolik. Biofilm meningkatkan virulensi bakteri dan membuatnya lebih sulit untuk dieliminasi. Lebih dari 90% bakteri dalam biofilm pada infeksi endodontik primer adalah bakteri anaerob. Perawatan saluran akar yang efektif harus mampu menghilangkan jaringan nekrotik dan mikroorganisme dalam biofilm untuk mencapai hasil perawatan yang maksimal. Proses cleaning and shaping, termasuk irigasi, sangat penting untuk menghilangkan smear layer dan mikroorganisme.
2. Porphyromonas gingivalis P. gingivalis Karakteristik dan Virulensi
Fokus utama beralih ke Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), bakteri anaerob obligat, berpigmen hitam, gram-negatif yang menginfeksi jaringan periapikal. Bakteri ini memiliki aktivitas proteolitik dan sering dikaitkan dengan abses periapikal. Penelitian menunjukkan prevalensi P. gingivalis yang tinggi (28% - 43,3%) pada pulpa dengan infeksi endodontik primer. P. gingivalis memiliki berbagai faktor virulensi patogenik, termasuk fimbriae, kapsul, vesikel ekstraseluler, hemaglutinin, gingipain, enzim hidrolitik, dan lipopolisakarida (LPS). LPS, sebagai endotoksin, mampu menembus jaringan periradikuler, memicu inflamasi dan kerusakan tulang melalui interaksi dengan lipopolisakarida binding protein (LBP) dan reseptor TLR4 pada makrofag, yang selanjutnya merangsang produksi sitokin seperti IL-1, IL-6, dan TNF-α. Infeksi silang P. gingivalis dengan bakteri lain, seperti Bacteroides forythus, meningkatkan risiko periodontitis apikalis kronis, dan kombinasi P. gingivalis dengan bakteri lainnya dapat meningkatkan risiko flare-up endodontik. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kultur menunjukkan prevalensi yang lebih rendah (10%-27,3%), namun dengan metode PCR, prevalensi yang lebih tinggi terdeteksi.
3. Kebutuhan Penelitian Lebih Lanjut tentang P. gingivalis dan Infeksi Endodontik Primer
Meskipun penelitian telah meneliti efek antibakteri ekstrak lerak terhadap bakteri lain seperti S. mutans, F. nucleatum, dan E. faecalis, serta efek antifungalnya terhadap C. albicans, belum ada penelitian yang meneliti efek antibakteri ekstrak lerak terhadap P. gingivalis pada infeksi endodontik primer. Penelitian ini dirasa penting karena P. gingivalis merupakan salah satu bakteri yang sering ditemukan pada infeksi endodontik primer. Sementara itu, penelitian menunjukkan bahwa irigasi dengan NaOCl dan CHX dapat mengeliminasi P. gingivalis secara signifikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efek antibakteri ekstrak lerak terhadap P. gingivalis dengan menentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) untuk mengevaluasi potensi ekstrak lerak sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar yang efektif dalam melawan bakteri ini dan mengatasi keterbatasan bahan irigasi sintetis yang sudah ada.
II.Bahan Irigasi Saluran Akar Ekstrak Lerak sebagai Alternatif
Berbagai bahan irigasi saluran akar seperti Sodium Hypochlorite (NaOCl), Chlorhexidine (CHX), dan Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) telah digunakan, tetapi masing-masing memiliki keterbatasan. Penelitian ini mengeksplorasi ekstrak lerak (Sapindus rarak DC), bahan alami dengan potensi antibakteri dan antifungal, sebagai alternatif bahan irigasi. Keunggulan ekstrak lerak terletak pada sifatnya yang ramah lingkungan dan potensi biokompatibilitasnya.
1. Keterbatasan Bahan Irigasi Saluran Akar Konvensional
Teks menjelaskan bahwa meskipun berbagai bahan irigasi saluran akar berupa larutan telah dikembangkan untuk memaksimalkan tindakan cleaning and shaping dalam perawatan endodonti, namun belum ada satu pun larutan irigasi yang mampu memenuhi seluruh kriteria ideal. Kriteria tersebut meliputi kemampuan melarutkan jaringan nekrotik dan smear layer, melumasi saluran akar, membunuh mikroorganisme, memiliki tegangan permukaan rendah, tidak toksik, dan tidak mengiritasi jaringan sehat. Selain itu, bahan irigasi yang ideal juga harus mudah diperoleh, relatif murah, mudah digunakan, mudah disimpan, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Bahan-bahan irigasi yang disebutkan dalam teks, seperti Mixture of tetracycline isomer, acid and detergent (MTAD), Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA), dan Chlorhexidine (CHX), masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. MTAD efektif mengeliminasi mikroorganisme resisten, tetapi kurang efektif melarutkan jaringan organik dan dapat menyebabkan noda pada jaringan keras gigi. EDTA efektif mendemineralisasi permukaan dentin dan menghilangkan smear layer, namun tidak efektif menghilangkan debris organik dan tidak memiliki efek antimikrobial. CHX biokompatibel dan memiliki efek antimikrobial yang luas, tetapi kurang efektif terhadap bakteri gram-negatif dan tidak dapat melarutkan jaringan nekrotik dan debris.
2. Ekstrak Lerak Sapindus rarak DC sebagai Alternatif Bahan Alami
Sebagai alternatif, penelitian ini memperkenalkan ekstrak lerak (Sapindus rarak DC) sebagai bahan alami yang berpotensi dikembangkan menjadi bahan irigasi saluran akar. Buah lerak, dikenal juga dengan berbagai nama daerah seperti rerek, werak/lerak, kalikea, kanikia, lamuran, dan buah sabun, secara tradisional digunakan sebagai pencuci kain batik dan emas, pembersih muka, dan obat penyakit kulit. Kandungan utama buah lerak adalah saponin triterpenoid, senyawa aktif permukaan yang bersifat seperti deterjen. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak lerak mengandung saponin dengan kadar lebih tinggi daripada buah lerak yang tidak diekstrak. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas antibakteri dan antifungal ekstrak lerak terhadap beberapa bakteri dan jamur, seperti Streptococcus mutans, Candida albicans, Fusobacterium nucleatum, dan Enterococcus faecalis. Namun, penelitian mengenai efek antibakteri ekstrak lerak terhadap Porphyromonas gingivalis masih belum ada, padahal bakteri ini sering ditemukan pada infeksi endodontik primer. Penelitian ini didorong oleh fokus pembangunan JAKSTRANAS IPTEK 2010-2014 pada teknologi kesehatan dan obat-obatan yang ramah lingkungan, dimana limbah obat-obatan alami lebih mudah terurai dibanding obat sintetis.
III.Metode Penelitian Penentuan Kadar Hambat Minimum KHM dan Kadar Bunuh Minimum KBM
Penelitian ini menggunakan metode dilusi untuk menguji efektivitas antibakteri dari ekstrak etanol lerak terhadap P. gingivalis. Tujuan utama adalah menentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak lerak. Pengujian dilakukan dengan berbagai konsentrasi ekstrak lerak dan diukur pertumbuhan bakteri setelah inkubasi 24 jam. Spesimen P. gingivalis yang digunakan adalah stem sel P. gingivalis ATCC 33277.
1. Metode Pengujian Antibakteri Metode Dilusi dan Drop Plate Miles Mesra
Penelitian ini menggunakan metode dilusi yang dikombinasikan dengan metode Drop Plate Miles Mesra untuk mengukur efektivitas antibakteri ekstrak etanol lerak terhadap Porphyromonas gingivalis. Metode dilusi melibatkan pengenceran ganda ekstrak lerak dalam pelarut etanol, menghasilkan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%, dan 1,625%. Konsentrasi ini dipilih berdasarkan standar pengujian antibakteri di Laboratorium Pusat Penyakit Tropis, UNAIR. Replikasi sebanyak 4 kali dilakukan pada setiap konsentrasi untuk meningkatkan akurasi hasil. Metode Drop Plate Miles Mesra kemungkinan besar digunakan dalam penentuan Kadar Bunuh Minimum (KBM), dimana jumlah koloni bakteri dihitung setelah inkubasi untuk menentukan persentase bakteri yang mati pada setiap konsentrasi. Ini berbeda dengan metode difusi, yang mengukur zona hambat pertumbuhan bakteri di sekitar disk antibiotik, dan metode ini dianggap kurang efektif dalam menginhibisi mikroorganisme karena ketergantungan pada kelarutan dan difusi bahan uji dalam media.
2. Penentuan Kadar Hambat Minimum KHM dan Kadar Bunuh Minimum KBM
Penentuan KHM dilakukan dengan mengamati kekeruhan pada tabung reaksi yang berisi ekstrak etanol lerak dan suspensi bakteri setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator CO2. KHM didefinisikan sebagai konsentrasi minimum ekstrak lerak yang mampu menghambat pertumbuhan P. gingivalis. Penggunaan spektrofotometer untuk mengukur kekeruhan dilakukan untuk membantu menentukan KHM, tetapi mengalami kendala karena warna coklat kehitaman ekstrak lerak membuat sulit untuk menentukan perubahan kekeruhan menjadi jernih. Penentuan KBM dilakukan dengan menghitung jumlah koloni bakteri pada media padat (MHA) setelah inkubasi. KBM adalah konsentrasi minimum bahan uji dimana setidaknya 99,9% bakteri mati. Pada penelitian ini, KBM ditentukan berdasarkan konsentrasi yang menyebabkan kematian 100% P.gingivalis karena kontrol positif (TBUD) membuat penetapan persentase kematian bakteri menjadi tidak mungkin pada konsentrasi tertentu. Metode perhitungan koloni bakteri menggunakan prinsip satu sel bakteri hidup akan tumbuh menjadi satu koloni bakteri pada media padat. Koloni P. gingivalis pada media padat berbentuk bulat dan berwarna putih keruh.
3. Persiapan Spesimen dan Media
Spesimen P. gingivalis yang digunakan adalah stem sel P. gingivalis ATCC 33277. Bakteri dibiakkan secara murni pada media MHA dalam suasana anaerob pada inkubator CO2 hingga diperoleh pertumbuhan yang sehat. Sebanyak 1-2 ose dari biakan murni bakteri disuspensikan dengan larutan 0,9% NaCl hingga diperoleh kekeruhan sesuai 0,5 McFarland Standard (setara dengan 1 x 108 CFU/ml). Media MHA (34 gram dalam 1 liter akuades) dibuat, disterilisasi dalam autoklaf, dan dituang ke dalam petri setelah dipanaskan kembali hingga mendidih sebelum digunakan untuk pembiakan spesimen. Sebelum pembiakan, media diinkubasi selama 24 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri. Pembuatan ekstrak etanol lerak dilakukan dengan melarutkan ekstrak kental lerak dalam etanol, dimulai dari konsentrasi 100%, kemudian dilakukan pengenceran berganda hingga konsentrasi 1,625%. Setiap tabung berisi 1 ml MHB.
IV. gingivalis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol lerak pada konsentrasi 100%, 50%, dan 25% mampu membunuh 100% P. gingivalis (steril). KBM ekstrak etanol lerak terhadap P. gingivalis ditetapkan pada konsentrasi 25%. Pada konsentrasi yang lebih rendah, pertumbuhan bakteri masih terdeteksi. Penentuan KHM menggunakan spektrofotometer mengalami kendala karena warna ekstrak yang pekat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan KHM dengan metode lain.
1. Efek Antibakteri Ekstrak Etanol Lerak terhadap P. gingivalis
Pengujian efek antibakteri ekstrak etanol lerak terhadap P. gingivalis dilakukan pada berbagai konsentrasi (100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%, dan 1,625%). Hasil menunjukkan pada konsentrasi 100%, 50%, dan 25%, pertumbuhan P. gingivalis terhambat sepenuhnya (steril, 0 CFU/ml). Ini mengindikasikan bahwa pada konsentrasi tersebut, semua bakteri P. gingivalis mati. Zona bening pada media MHA mendukung temuan ini. Pada konsentrasi 12,5% dan 6,25%, terdapat pertumbuhan koloni bakteri, dengan rata-rata (1,18 x 10³ ± 0,29 x 10³) CFU/ml dan (2,62 x 10³ ± 0,77 x 10³) CFU/ml, berturut-turut. Sementara itu, pada konsentrasi 3,125% dan 1,625%, pertumbuhan bakteri masih subur dan tumpang tindih sehingga jumlahnya tidak dapat dihitung (TBUD). Berdasarkan hasil ini, Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak etanol lerak terhadap P. gingivalis ditetapkan pada 25%, karena pada konsentrasi ini 100% bakteri mati. Data hasil uji ini diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk dan dilanjutkan dengan uji one way ANOVA dan LSD karena data terdistribusi normal.
2. Penentuan Kadar Hambat Minimum KHM dan Kendala Pengukuran
Penentuan Kadar Hambat Minimum (KHM) mengalami kendala karena warna ekstrak etanol lerak yang coklat kehitaman. Warna ini menyebabkan suspensi bakteri dan ekstrak menjadi coklat keruh, sehingga sulit untuk secara visual menentukan konsentrasi dimana kekeruhan mulai berkurang atau larutan tampak jernih. Metode pengukuran KHM menggunakan spektrofotometer, dengan membandingkan kekeruhan tabung reaksi dengan kontrol. Karena kendala ini, nilai KHM tidak dapat ditentukan secara representatif dalam penelitian ini, dan peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut untuk menentukan KHM dengan metode yang lebih tepat. Analisis statistik lebih lanjut, seperti uji one way ANOVA dan LSD, dilakukan untuk membandingkan perbedaan signifikansi antara beberapa konsentrasi ekstrak etanol lerak, dengan nilai p=0.000 (p<0.05) menunjukkan perbedaan signifikan antara konsentrasi yang diuji.
V.Pembahasan Mekanisme Kerja dan Keterbatasan Penelitian
Efek antibakteriekstrak lerak diduga disebabkan oleh kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Saponin berperan sebagai surfaktan, mengganggu permeabilitas sel bakteri. Penelitian ini memiliki keterbatasan, salah satunya adalah penggunaan etanol teknis yang kurang murni dan pengeringan kulit lerak yang terlalu lama. Hal ini perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan pelarut metanol juga dibahas.
1. Mekanisme Kerja Antibakteri Ekstrak Etanol Lerak
Efek antibakteri ekstrak etanol lerak terhadap P. gingivalis, dan juga bakteri lainnya seperti S. mutans, F. nucleatum, dan E. faecalis, diperkirakan disebabkan oleh senyawa aktif yang terkandung di dalamnya, yaitu saponin, flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Saponin, yang bertindak sebagai surfaktan atau deterjen, menyerang lapisan batas sel bakteri melalui ikatan gugus polar saponin dengan polisakarida dan peptidoglikan, serta gugus non-polar saponin dengan LTA. Hal ini menyebabkan gangguan permeabilitas sel, gangguan fungsi sel, lisis sel, dan akhirnya kematian bakteri. Flavonoid diduga merusak membran sel karena sifatnya yang lipofilik dan kemampuannya membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler. Senyawa fenol bersifat toksik terhadap mikroorganisme karena dapat menghambat enzim penting, mengganggu fungsi sel, dan merusak protein, sehingga mengganggu semipermeabilitas membran sel. Alkaloid juga bersifat toksik dan dapat melawan sel bakteri.
2. Keterbatasan dan Kesalahan dalam Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kesalahan. Penggunaan etanol teknis 96% yang telah diencerkan menjadi 70% merupakan salah satu kelemahan. Seharusnya, etanol pro analis (>99,5%) digunakan karena kemurniannya yang lebih tinggi memastikan konsentrasi ekstrak yang tepat. Etanol teknis yang kurang murni kemungkinan menyebabkan kandungan air dan zat terlarut lain yang tinggi dalam ekstrak, sehingga mempengaruhi konsentrasi sebenarnya saat ekstrak diencerkan dalam MHB. Hal ini dapat menyebabkan nilai KBM yang diperoleh (25%) menjadi lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Selain itu, ketidakpastian mengenai umur buah lerak yang digunakan dan proses pengeringan yang terlalu lama (sekitar 7 minggu) pada penelitian sebelumnya juga dapat mempengaruhi kualitas dan komposisi zat aktif dalam ekstrak. Perbedaan pelarut yang digunakan untuk maserasi simplisia lerak (metanol pada penelitian sebelumnya, etanol pada penelitian ini) dan asal geografis buah lerak juga dapat menyebabkan perbedaan hasil penelitian.
