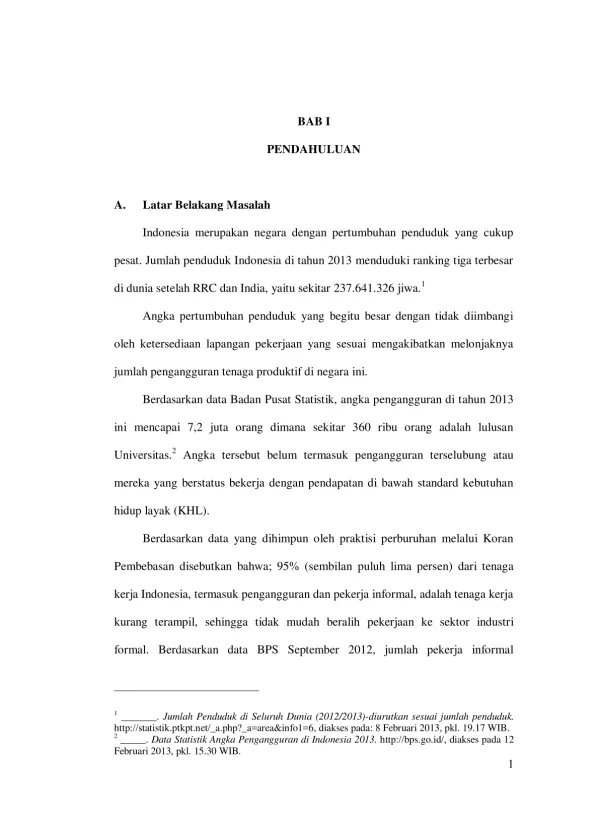
Analisis Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2013
Informasi dokumen
| Jurusan | Ilmu Sosial/Ketenagakerjaan |
| Jenis dokumen | Esai/Makalah |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 1.03 MB |
- Pertumbuhan Penduduk
- Pengangguran
- Ketenagakerjaan Informal
Ringkasan
I.Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia Angka Pengangguran dan Pekerja Informal yang Tinggi
Dokumen ini membahas permasalahan serius ketenagakerjaan di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan jumlah pekerja informal. Data menunjukkan sekitar 95% tenaga kerja Indonesia, termasuk pengangguran dan pekerja informal, merupakan tenaga kerja kurang terampil. Pada September 2012, BPS mencatat jumlah pekerja informal yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, memperparah situasi. Prakarsa mencatat sekitar 103,2 juta orang bekerja di sektor informal dan setengah pengangguran dari total 149,8 juta tenaga kerja, sementara 7,2 juta orang berstatus pengangguran (data sebelum kenaikan BBM 2013). Jumlah pekerja informal meningkat hingga 1 juta orang pada 2013 sebelum kenaikan BBM. Keadaan ini menyebabkan rendahnya nilai tawar pekerja dan berpotensi memicu perselisihan hubungan industrial.
1. Tingginya Persentase Tenaga Kerja Kurang Terampil
Data dari praktisi perburuhan melalui Koran Pembebasan menunjukkan fakta mengejutkan: 95% tenaga kerja Indonesia, termasuk pengangguran dan pekerja informal, masuk kategori kurang terampil. Keterbatasan keahlian ini menjadi penghalang utama bagi mereka untuk beralih ke sektor industri formal yang lebih menjanjikan. Kondisi ini memperburuk masalah pengangguran dan memperkuat dominasi pekerja informal di pasar tenaga kerja Indonesia. Minimnya keterampilan ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan formal menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Hal ini juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara mereka yang memiliki keterampilan dan yang tidak.
2. Pertumbuhan Penduduk dan Keterbatasan Lapangan Kerja
Indonesia menghadapi tantangan besar berupa pertumbuhan penduduk yang pesat. Pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat ketiga negara terpadat di dunia setelah RRC dan India, dengan jumlah penduduk sekitar 237.641.326 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk yang signifikan ini, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, terutama di kalangan tenaga kerja produktif. Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak menjadi akar permasalahan utama dalam sektor ketenagakerjaan Indonesia. Minimnya lapangan kerja formal memaksa banyak angkatan kerja untuk mencari nafkah di sektor informal yang seringkali tidak memberikan jaminan penghasilan yang stabil dan memadai. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meluas.
3. Dampak Kebijakan Ekonomi dan Kenaikan BBM
Kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan yang dianggap non-populis, turut mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa waktu lalu. Kenaikan BBM ini berdampak langsung pada peningkatan harga barang dan jasa, sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kesempatan kerja dan peningkatan jumlah pengangguran, terutama di sektor informal. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil justru semakin memperparah kondisi perekonomian dan semakin memperluas angka pengangguran serta pekerja informal. Kenaikan BBM juga berdampak pada daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) yang sebagian besar menyerap tenaga kerja informal, sehingga semakin memperburuk masalah pengangguran.
4. Data Statistik Ketenagakerjaan dari Prakarsa dan BPS
Data dari Prakarsa menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sekitar 103,2 juta orang bekerja di sektor informal dan setengah pengangguran dari total 149,8 juta tenaga kerja di Indonesia. Sebanyak 7,2 juta orang tercatat sebagai pengangguran (data satu bulan sebelum kenaikan BBM). Angka-angka ini diperkirakan akan meningkat sebagai dampak dari kenaikan BBM. Jumlah setengah pengangguran juga terus meningkat setiap tahunnya. Prakarsa juga mencatat peningkatan jumlah pekerja sektor informal sebesar 1 juta orang pada tahun 2013 sebelum kenaikan BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2013 mencapai 121,2 juta orang, meningkat 780 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya. Data BPS pada Agustus 2013 menunjukkan jumlah pekerja informal mencapai 66 juta jiwa (59,58%), sementara pekerja formal berjumlah 44,8 juta jiwa (40,42%). Data ini menunjukkan dominasi pekerja informal dan menggambarkan besarnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia.
II.Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Ketenagakerjaan dan Peran UU Ketenagakerjaan
Kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan BBM, berpengaruh signifikan terhadap dunia kerja. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Program-program pemerintah seperti Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) dengan target penurunan angka pengangguran hingga 5,1% pada akhir 2014, pengembangan wirausaha, dan bursa kerja (job fair) terus diupayakan untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM. Namun, peningkatan kasus perselisihan hubungan industrial hingga 27% dari 2012 hingga 2013 menunjukkan masih lemahnya perlindungan hak pekerja.
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai Landasan Kebijakan
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini merupakan implementasi dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meskipun terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan masih kompleks dan belum terselesaikan sepenuhnya, terutama terkait hak-hak dasar pekerja. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan hingga perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, hingga ketentuan pidana dan sanksi administratif. Namun, permasalahan seperti sistem outsourcing tetap menjadi tantangan besar dalam implementasi Undang-Undang ini.
2. Upaya Pemerintah dalam Menekan Angka Pengangguran
Pemerintah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program. Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) dicanangkan dengan target penurunan angka pengangguran hingga 5,1% pada akhir tahun 2014. Selain GPP, pemerintah juga berupaya membuka lapangan pekerjaan baru di sektor formal maupun informal, memprioritaskan penciptaan lapangan kerja (job creation) yang dipadukan dengan program pemberdayaan masyarakat. Program padat karya, pengembangan wirausaha produktif, dan peningkatan pelaksanaan bursa kerja (job fair) oleh pemerintah dan swasta juga menjadi bagian dari strategi ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membangun kompetensi (skill, knowledge, attitude) tenaga kerja agar memiliki daya saing dan mampu menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha mandiri. Namun, peningkatan kasus perselisihan hubungan industrial menunjukkan bahwa upaya-upaya ini masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak pekerja.
3. Perkembangan UU Ketenagakerjaan dan Dampaknya
Peraturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan, dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perubahan ini merupakan dampak dari reformasi tahun 1998 yang menghasilkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR ini menjadi tonggak penting dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Meskipun terdapat banyak aturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, belum semua masalah dapat terselesaikan secara tuntas, terutama yang terkait dengan hak-hak dasar pekerja. Salah satu permasalahan yang masih menjadi kendala adalah sistem outsourcing yang cenderung memicu likuidasi hak-hak dasar pekerja dan peningkatan status pekerja outsourcing dari tahun ke tahun. Konflik dan kontradiksi antara pekerja dan pemberi kerja dalam perselisihan hubungan industrial masih menjadi pemandangan umum.
4. Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan data dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), kasus perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha meningkat hingga 27% dari tahun 2012 hingga 2013. Peningkatan ini dipicu oleh merosotnya situasi ekonomi dalam negeri akibat resesi ekonomi global sejak tahun 2009. Perselisihan tersebut seringkali berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan sepihak. Setelah melakukan PHK, perusahaan seringkali merekrut tenaga kerja baru dengan status kontrak dan outsourcing, menunjukkan lemahnya perlindungan hak atas kepastian kerja bagi pekerja di Indonesia. PHK sepihak dapat terjadi sewaktu-waktu, sementara pengusaha masih mudah memperoleh tenaga kerja baru dengan hak yang lebih longgar. Ini menggambarkan betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia.
III.Permasalahan Pekerja Outsourcing di Indonesia
Sistem outsourcing menjadi isu sentral dalam dokumen ini. Meskipun diklaim mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi perusahaan, praktiknya seringkali merugikan pekerja. Data ILO Desember 2010 menunjukkan 65% buruh di Indonesia berstatus kontrak dan outsourcing, dengan banyaknya perusahaan outsourcing abal-abal. Sistem ini mengaburkan hubungan kerja, melemahkan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk jaminan kepastian kerja, dan menimbulkan eksploitasi, terutama terhadap buruh perempuan. Kasus CV. Jaya Mandiri yang melibatkan pekerja outsourcing tanpa kontrak kerja tertulis dan perselisihan yang berujung ke Mahkamah Agung menjadi contoh nyata permasalahan ini. Putusan Mahkamah Agung No.018 K/Pdt.Sus/2009 menegaskan bahwa CV. Jaya Mandiri belum memenuhi syarat sebagai penyedia jasa outsourcing sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (3).
1. Statistik Pekerja Outsourcing di Indonesia
Data dari ILO pada Desember 2010 menunjukkan fakta mengejutkan terkait pekerja outsourcing di Indonesia. Sebanyak 65% dari seluruh buruh di Indonesia berstatus kontrak atau outsourcing, meninggalkan hanya 35% yang berstatus sebagai buruh tetap. Angka ini menggambarkan besarnya ketergantungan pada sistem outsourcing dan implikasinya terhadap stabilitas dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, jumlah perusahaan outsourcing yang beroperasi juga mengalami peningkatan, mencapai 1200 perusahaan pada tahun 2011. Yang lebih mengkhawatirkan, 80% dari perusahaan tersebut dinilai sebagai perusahaan abal-abal atau tidak jelas legalitasnya, menunjukkan kerentanan dan ketidakpastian hukum yang dihadapi pekerja outsourcing. Buruh outsourcing seringkali diperlakukan sebagai komoditas yang mudah diperjualbelikan, situasi yang diperparah oleh peran pemerintah yang dianggap sebagai broker bagi para pemodal. Kondisi ini membuat sistem outsourcing dianggap sebagai perbudakan modern.
2. Dampak Outsourcing terhadap Buruh Perempuan
Sistem outsourcing juga memperburuk penindasan terhadap buruh perempuan. Mereka cenderung mendominasi pekerjaan rendah skill yang membutuhkan ketelitian, bukan pekerjaan berbasis keahlian. Pekerjaan ini biasanya disertai kondisi kerja yang jauh lebih buruk. Dominasi buruh perempuan di sektor informal juga cukup tinggi, mencapai 54,82% dari seluruh jumlah buruh perempuan atau sekitar 40 juta jiwa. Kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan ketidakpastian kerja semakin memperparah kesenjangan gender di dunia kerja Indonesia. Sistem outsourcing yang tidak terkontrol justru memperparah eksploitasi terhadap buruh perempuan yang telah rentan secara ekonomi dan sosial. Hal ini memerlukan perhatian khusus dan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi buruh perempuan dari dampak negatif sistem outsourcing.
3. Ketidakpastian Hubungan Kerja dan Perlindungan Pekerja Outsourcing
Perusahaan outsourcing biasanya membuat perjanjian kontrak dengan pekerja hanya selama pekerjaan tersedia. Jika kontrak berakhir, hubungan kerja juga berakhir. Praktik ‘no work no pay’ sering diterapkan, artinya pekerja tidak digaji selama tidak bekerja, meskipun hubungan kerja telah berlangsung lama. Perlindungan kerja bagi pekerja outsourcing sangat lemah dibandingkan pekerja tetap (non-outsourcing). Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan utama (principal) seringkali tidak dibuat secara tertulis, menyebabkan status pekerja menjadi tidak jelas dan rentan terhadap PHK sekehendak perusahaan tanpa pesangon. Ketidakjelasan hubungan kerja ini menciptakan kerentanan hukum dan ekonomi bagi pekerja outsourcing, membuat mereka mudah dieksploitasi dan tidak memiliki jaminan kepastian kerja.
4. Studi Kasus CV. Jaya Mandiri dan Implikasinya
Kasus CV. Jaya Mandiri, sebuah perusahaan yang bukan berbadan hukum, menjadi contoh nyata permasalahan pekerja outsourcing di Indonesia. Pekerja CV. Jaya Mandiri, yang bekerja sebagai satpam di Hotel Amanda, mengalami perselisihan dengan perusahaan karena berbagai alasan, termasuk pembayaran gaji yang tidak sesuai, status kerja yang tidak jelas (kontrak), dan keengganan perusahaan untuk menandatangani perjanjian kerja tertulis. Perselisihan ini berlanjut hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K/Pdt.Sus/2009 menyatakan bahwa CV. Jaya Mandiri tidak memenuhi syarat sebagai penyedia jasa outsourcing karena tidak berbadan hukum sesuai Pasal 66 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya badan hukum yang jelas bagi perusahaan outsourcing dan perlunya perjanjian kerja tertulis untuk melindungi hak-hak pekerja outsourcing.
IV.Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dan Perjanjian Kerja
Dokumen ini menganalisis kedudukan hukum pekerja outsourcing, terutama yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan vendor yang tidak berbadan hukum. UU Ketenagakerjaan mengatur tentang perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan, namun implementasinya seringkali tidak melindungi pekerja outsourcing. Ketidakjelasan status pekerja outsourcing dan minimnya perlindungan hukum membuat mereka rentan terhadap PHK sepihak tanpa pesangon. Hubungan kerja yang tidak jelas antara pekerja, vendor, dan principal (perusahaan utama) menciptakan ketidakpastian dan kerentanan bagi pekerja. Studi kasus CV. Jaya Mandiri dan Putusan Mahkamah Agung menjadi acuan dalam menganalisis masalah ini. Pentingnya perjanjian kerja tertulis dan badan hukum yang jelas bagi perusahaan vendor menjadi sorotan utama untuk melindungi hak-hak pekerja outsourcing.
1. Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja dalam Konteks Hukum Indonesia
Dalam konteks hukum Indonesia, hubungan kerja didasarkan pada hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha. Dasar hukumnya adalah perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Sistem ini telah dianut sejak berlakunya Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Pasal 51 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, meskipun pada prinsipnya perjanjian kerja tertulis lebih diutamakan. Adanya pekerjaan di bawah perintah orang lain menunjukkan hubungan subordinasi (dienstverhouding), yaitu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan perintah pengusaha. Hidayat Muharam berpendapat bahwa perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis, terutama karena beberapa bentuk perjanjian kerja mengecualikan asas konsensualitas dan dipersyaratkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis. Namun, kenyataannya banyak pekerja yang sudah bekerja dan menerima upah namun belum menandatangani perjanjian kerja tertulis.
2. Kedudukan Hukum Pekerja Outsourcing dengan Vendor yang Bukan Berbadan Hukum
Pasal 66 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa penyedia jasa pekerja/buruh harus berupa bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang bukan berbadan hukum. Studi kasus CV. Jaya Mandiri, sebuah perusahaan non-badan hukum, menunjukkan permasalahan ini. Pekerja CV. Jaya Mandiri yang bertugas sebagai satpam di Hotel Amanda mengalami perselisihan hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 018 K/Pdt.Sus/2009 menegaskan bahwa CV. Jaya Mandiri tidak memenuhi syarat sebagai penyedia jasa outsourcing karena belum memenuhi persyaratan sebagai penyedia jasa outsourcing sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (3) jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 101/MEN/VI/2004 Pasal 2 ayat (2). Kasus ini menunjukkan kerentanan pekerja yang berhubungan dengan vendor yang tidak berbadan hukum.
3. Perlindungan Hukum yang Lemah dan Ketidakjelasan Status Pekerja Outsourcing
Perlindungan kerja bagi pekerja outsourcing sangat lemah dibandingkan pekerja tetap. Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan utama (principal) seringkali tidak dibuat secara tertulis, mengakibatkan ketidakjelasan status pekerja. Ketidakjelasan ini membuat pekerja outsourcing mudah di-PHK tanpa uang pesangon. Aloysius Uwiyono berpendapat bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha. Namun, dalam praktiknya, ketidakadaan perjanjian kerja tertulis, terutama dalam skema outsourcing yang melibatkan tiga pihak (pekerja, vendor, dan principal), menciptakan celah hukum yang merugikan pekerja outsourcing. Mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Ketidakjelasan status ini juga mengaburkan hak-hak pekerja di tempat mereka bekerja, termasuk jaminan kepastian kerja.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kasus CV. Jaya Mandiri menunjukkan bagaimana lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing yang tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan bekerja dengan vendor yang tidak berbadan hukum. Mediasi antara pekerja dan vendor mungkin menghasilkan kesepakatan perubahan status dari kontrak menjadi tetap, namun hal ini tidak menjamin peralihan hubungan kerja dengan principal jika principal menolak. Ketidakjelasan ini menyoroti pentingnya perjanjian kerja tertulis dan badan hukum yang jelas untuk melindungi pekerja outsourcing. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kedudukan hukum pekerja outsourcing yang terikat pada perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing (vendor) yang tidak berbadan hukum agar kasus serupa dapat diselesaikan dengan adil. Aparatur penegak hukum, termasuk Dinas Tenaga Kerja, harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan iklim hubungan industrial yang adil.
Referensi dokumen
- Hubungan Industrial (Industrial Relation) (Agus Guntur PM)
- Dinamika Ketentuan Hukum tentang Pesangon (Aloysius Uwiyono)
- Kedudukan Outsourcing di Indonesia (Erlangga Negara)
- Akhir 2013, Muhaimin Targetkan Pengangguran Turun (K. Yudha Wirakusuma)
