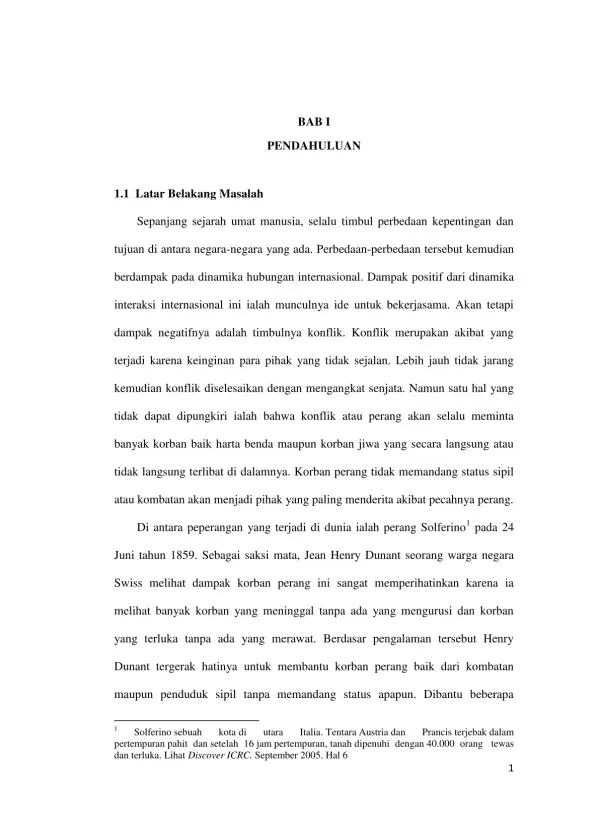
Peran ICRC dalam Penanganan Korban Perang dan Konflik
Informasi dokumen
| Sekolah | Tidak disebutkan dalam dokumen |
| Jurusan | Hubungan Internasional, Hukum Humaniter Internasional, atau studi terkait |
| Tahun terbit | Tidak disebutkan secara spesifik, namun merujuk pada periode sejarah yang panjang, termasuk kejadian di tahun 1859, 1953, 1976 dan seterusnya. |
| Tempat | Tidak disebutkan dalam dokumen |
| Jenis dokumen | Esai, makalah, atau bagian dari buku teks |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 317.22 KB |
- konflik internasional
- bantuan kemanusiaan
- Hukum Humaniter Internasional
Ringkasan
I.Peran ICRC dalam Konflik Bersenjata di Aceh melalui Program Restoring Family Links RFL
Skripsi ini meneliti peran penting Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam konflik Aceh (1989-2005), khususnya melalui program Restoring Family Links (RFL) atau Pemulihan Hubungan Keluarga. Program ini sangat krusial karena konflik bersenjata menyebabkan pemisahan keluarga, baik korban perang sipil maupun kombatan. ICRC, sebagai organisasi kemanusiaan internasional yang independen dan netral, berperan dalam menghubungkan kembali keluarga yang terpisah akibat konflik melalui berbagai cara, termasuk pertukaran pesan Palang Merah dan kunjungan keluarga ke tahanan. Penelitian ini menganalisis dampak program RFL terhadap korban konflik, menekankan pentingnya aksi kemanusiaan dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam situasi krisis.
1. Latar Belakang Konflik Aceh dan Kebutuhan Restoring Family Links
Bagian ini menjelaskan konteks konflik bersenjata di Aceh antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Konflik berkepanjangan ini mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi penduduk sipil, dengan ribuan menjadi janda, duda, dan yatim piatu. Kerugian ekonomi juga signifikan karena penurunan daya beli masyarakat dan dampak psikologis berupa trauma. Penulis menekankan bahwa konflik ini menyebabkan banyak keluarga terpisah, baik sipil maupun kombatan. Kebutuhan mendesak akan informasi tentang anggota keluarga yang hilang menjadi prioritas utama. Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya peran ICRC melalui program Restoring Family Links (RFL) untuk membantu memulihkan hubungan keluarga yang terputus akibat konflik tersebut. Dokumen ini mencatat bahwa konflik di Aceh, meskipun unik, memiliki kesamaan dengan konflik di berbagai belahan dunia lainnya; yaitu potensi pemisahan keluarga dan kebutuhan akan informasi tentang keberadaan anggota keluarga yang terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran ICRC dalam konflik bersenjata di Aceh melalui program RFL.
2. Peran ICRC dalam Pemulihan Hubungan Keluarga RFL di Aceh
Bagian ini menjabarkan secara rinci bagaimana ICRC menjalankan program Restoring Family Links (RFL) di Aceh. ICRC, sebagai organisasi netral dan tidak memihak, bekerja sama dengan perhimpunan nasional (Palang Merah Indonesia) untuk membantu korban konflik. Program RFL ini didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional dan bertujuan untuk mereunifikasi keluarga yang terpisah akibat konflik. Metode yang digunakan meliputi pertukaran pesan Palang Merah dan fasilitasi kunjungan keluarga ke tahanan. ICRC memfasilitasi komunikasi antara tahanan dengan keluarga mereka, baik melalui telepon, pesan tertulis, maupun kunjungan langsung. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan psikologis para tahanan dan keluarga mereka, terutama karena situasi konflik menciptakan kepanikan dan ketidakpastian. Dokumen tersebut juga mencontohkan pengalaman serupa ICRC di Liberia dan Somalia, di mana program RFL juga berhasil menghubungkan kembali banyak anak-anak dengan orang tua mereka melalui berbagai metode, termasuk penggunaan telepon seluler yang dinilai efektif dan efisien di daerah konflik.
3. Kerangka Hukum dan Landasan Teoritis Peran ICRC
Bagian ini membahas landasan hukum dan teoritis yang mendasari peran ICRC dalam konflik Aceh. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi acuan utama ICRC dalam menjalankan operasi kemanusiaan di daerah konflik, termasuk Aceh. Pasal 26 Konvensi Jenewa IV, yang menekankan pentingnya memfasilitasi pencarian anggota keluarga yang terpisah akibat perang, menjadi rujukan penting dalam program RFL. Dokumen ini juga mengklasifikasikan ICRC sebagai bagian dari Global Civil Society, sebuah jaringan organisasi independen yang berperan dalam dinamika hubungan internasional. ICRC memanfaatkan kemajuan teknologi dan globalisasi untuk memperluas jangkauan dan dampak programnya, termasuk upaya untuk menyebarkan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian terdahulu tentang peran ICRC di Indonesia lebih berfokus pada aspek hukum internasional, sedangkan penelitian ini mendalami program RFL secara spesifik dalam konteks konflik Aceh. Kesimpulannya, ICRC beroperasi berdasarkan mandat internasional untuk melindungi korban konflik bersenjata, dan program RFL di Aceh merupakan implementasi nyata dari komitmen tersebut berdasarkan HHI dan peran ICRC dalam Global Civil Society.
4. Metodologi Penelitian dan Analisis Data
Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan batasan waktu 1989-2005, periode eskalasi konflik di Aceh. Analisis data kualitatif difokuskan pada program RFL ICRC, guna mendeskripsikan dan menjelaskan peran ICRC dalam konflik tersebut. Metode analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memaparkan secara mendalam program Restoring Family Links ICRC dalam konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan GAM. Penelitian ini tidak menggunakan metode statistik, karena data yang dianalisis berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam peran ICRC dalam program RFL, terutama dampaknya terhadap korban konflik dan keluarga mereka yang terpisah. Argumen dasar penelitian berlandaskan pada hukum humaniter internasional dan mandat ICRC dalam memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.
II.Konflik Aceh dan Dampak Kemanusiaannya
Konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia (1989-2005) mengakibatkan penderitaan besar bagi penduduk sipil. Ribuan orang menjadi janda, duda, dan yatim piatu. Kerugian ekonomi juga signifikan, dengan penurunan daya beli dan dampak psikologis jangka panjang berupa trauma. Situasi ini mendorong kebutuhan mendesak akan aksi kemanusiaan, termasuk upaya reunifikasi keluarga.
1. Sejarah dan Eskalasi Konflik Aceh
Bagian ini membahas sejarah konflik Aceh yang panjang dan kompleks, dimulai sejak tahun 1950-an hingga tahun 2005. Dokumen menyebutkan beberapa periode penting, termasuk periode DI/TII (1953-1963), konflik politik 1965 (1965-1970), pra-DOM (1976-1989), DOM (1989-1998), dan pasca-pencabutan status DOM (1998-2005). Konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penggabungan Aceh ke dalam Gerakan Darul Islam pada tahun 1953 dan kebijakan pemerintah Indonesia seperti Daerah Operasi Militer (DOM). Eskalasi konflik ini ditandai dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tindakan represif pemerintah, yang mengakibatkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil dan korban dari kedua belah pihak. Data dari Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh menunjukkan rentang waktu kekerasan yang panjang dan berkelanjutan, memperparah penderitaan penduduk sipil. Periode 1989-2005 menjadi fokus penelitian karena eskalasi konflik yang tinggi pada masa tersebut, sehingga potensi korban dan pemisahan keluarga sangat besar.
2. Dampak Kemanusiaan Konflik Aceh
Konflik bersenjata di Aceh telah menyebabkan penderitaan yang sangat nyata bagi penduduk sipil. Ribuan wanita menjadi janda karena suami mereka dibunuh atau diculik, dan banyak anak-anak menjadi yatim piatu. Kondisi ekonomi masyarakat Aceh juga mengalami kemerosotan yang drastis. Daya beli masyarakat menurun, pasar sepi karena masyarakat takut keluar rumah, dan pedagang enggan mendatangkan barang karena risiko keamanan yang tinggi. Semua ini menyebabkan trauma psikologis yang meluas dan berkepanjangan di masyarakat Aceh. Dokumen ini menekankan betapa besarnya penderitaan dan kerugian yang diakibatkan oleh konflik, baik berupa korban jiwa dan harta benda, maupun dampak psikologis jangka panjang. Kerusakan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh konflik ini sangat signifikan, dan menjadi salah satu alasan utama mengapa intervensi kemanusiaan, termasuk program reunifikasi keluarga, sangat penting.
3. Konflik Aceh sebagai Isu Internasional dan Peran ICRC
Akibat konflik yang berkepanjangan dan jumlah korban yang banyak, konflik Aceh dengan cepat menjadi perhatian internasional. Hal ini mendorong ICRC untuk melakukan operasi kemanusiaan di Aceh, terutama melalui program reunifikasi keluarga yang disebut Restoring Family Links (RFL). Program RFL ICRC didasarkan pada kenyataan bahwa baik penduduk sipil maupun kombatan menjadi korban konflik dan berpotensi terpisah dari keluarga mereka. Kondisi di mana penduduk sipil berada di tengah-tengah peperangan tanpa pihak penengah, kecuali pihak ketiga, meningkatkan potensi pemisahan keluarga. Konflik bersenjata menimbulkan lebih dari sekadar luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan pemisahan keluarga. Dokumen ini mencatat berbagai alasan mengapa keluarga dapat terpisah selama konflik, mulai dari kehilangan jejak satu sama lain saat melarikan diri hingga penculikan dan pembunuhan, yang seringkali menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi korban. Peran ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya program RFL, sangat vital dalam situasi ini.
III.ICRC dan Operasi Kemanusiaannya di Indonesia
ICRC telah beroperasi di Indonesia sejak 1950, dengan perjanjian bilateral resmi pada 1977 (MoU 1977) dan 1987 (Agreement 1987). Kerjasama ini meliputi kunjungan ke tahanan, pertolongan bencana alam, penyebaran Hukum Humaniter Internasional (HHI), dan upaya pencarian orang hilang melalui Central Tracing Agency (CTA). Di Aceh, ICRC menjalankan program RFL sebagai bagian dari upaya aksi kemanusiaan yang lebih luas.
1. Sejarah Kerjasama ICRC dan Pemerintah Indonesia
Dokumen ini menjelaskan bahwa kerjasama antara ICRC dan Pemerintah Indonesia telah berlangsung lama, dimulai sejak tahun 1950, meskipun perjanjian bilateral resmi baru disepakati pada tahun 1977 (MoU 1977) dan diperkuat pada tahun 1987 (Agreement 1987). Sebelum 1977, kerjasama telah terjalin melalui berbagai kegiatan. MoU 1977 mengizinkan ICRC mengunjungi tahanan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sementara itu, Agreement 1987 memungkinkan ICRC untuk membuka kantor delegasi regional di Jakarta. Kerjasama ini menunjukkan komitmen jangka panjang antara ICRC dan Indonesia dalam hal kemanusiaan dan penegakan hukum humaniter internasional. Sejak didirikan pada tahun 1863, ICRC telah beroperasi di lebih dari delapan puluh negara, menunjukkan jangkauan global organisasi ini dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Di Indonesia, kerjasama ini mencakup berbagai bidang, termasuk kunjungan ke tahanan, pertolongan terhadap bencana alam, dan penyebaran Hukum Humaniter Internasional.
2. Peran Central Tracing Agency CTA dalam Operasi ICRC di Indonesia
Sejak tahun 1977, ICRC di Indonesia juga menjalankan tugas melalui Central Tracing Agency (CTA). CTA dibentuk untuk meringankan penderitaan mental keluarga yang terpisah akibat konflik bersenjata, terutama berkaitan dengan tawanan perang. Awalnya, CTA fokus pada penelusuran tawanan perang, namun seiring waktu, cakupan tugasnya meluas mencakup berbagai kasus pemisahan keluarga karena perang, ketegangan dalam negeri, dan bencana. Operasi CTA di lokasi pengungsian meliputi penyaluran informasi kepada keluarga melalui rilis daftar orang hilang dan keluarga yang mencari anggota keluarganya. Pusat CTA di Jenewa menyimpan arsip yang sangat rahasia tentang nama-nama tawanan, pengungsi, dan orang hilang. CTA bekerja sama erat dengan perhimpunan nasional di masing-masing negara untuk memfasilitasi rekonsiliasi keluarga. Dengan menghubungkan kembali komunikasi yang terputus antar keluarga, CTA berupaya meringankan beban psikologis yang diakibatkan oleh konflik dan ketidakpastian.
3. Operasi ICRC di Indonesia Sebelum dan Sesudah 1977
Penulis Agustinus Supriyanto membagi masa pelaksanaan tugas ICRC di Indonesia menjadi dua periode: sebelum dan sesudah tahun 1977. Meskipun perjanjian bilateral baru disepakati pada tahun 1977, kerjasama ICRC dengan pemerintah Indonesia telah terjalin sejak tahun 1950. Kegiatan sebelum tahun 1977 antara lain mencakup upaya-upaya yang meletakkan dasar untuk kerjasama yang lebih formal dan terstruktur di masa mendatang. Setelah tahun 1977, kerjasama semakin intensif dan terinstitusionalisasi melalui MoU 1977 dan Agreement 1987. Hal ini menunjukkan perkembangan kerja sama antara ICRC dan pemerintah Indonesia dalam bidang kemanusiaan, perlindungan, dan penegakan Hukum Humaniter Internasional. Peran ICRC yang mencakup berbagai aspek kemanusiaan, seperti kunjungan ke tahanan, bantuan bencana alam, dan penyebaran Hukum Humaniter Internasional, menunjukkan komitmen organisasi ini terhadap kesejahteraan kemanusiaan di Indonesia.
IV.ICRC sebagai Aktor dalam Global Civil Society
ICRC diklasifikasikan sebagai bagian dari Global Civil Society, sebuah jaringan organisasi independen yang bekerja di luar area kelembagaan negara. ICRC memanfaatkan arus globalisasi untuk mempromosikan HHI dan memberikan aksi kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk di Aceh. Organisasi ini bertindak sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional, bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lainnya untuk mencapai tujuan kemanusiaannya.
1. ICRC dan Konsep Global Civil Society
Bagian ini menjelaskan klasifikasi ICRC sebagai bagian dari Global Civil Society. Global Civil Society didefinisikan sebagai ruang ide, nilai, organisasi, dan individu yang berada di luar kompleks kelembagaan keluarga, pasar, dan negara, serta melampaui batas-batas nasional, politik, dan ekonomi. Dua unsur penting Global Civil Society adalah keberadaannya di luar area kelembagaan negara dan gerakannya yang transnasional. Anthony Giddens menghubungkan Global Civil Society erat dengan globalisasi, yang mempersempit ruang dan waktu, sehingga batas teritorial negara menjadi kurang relevan. Globalisasi juga meningkatkan kesadaran global akan isu-isu kemanusiaan. Global Civil Society mencakup berbagai aktor transnasional, termasuk NGO, kelompok penekan, gerakan sosial, dan jaringan advokasi. ICRC, dengan keunikan statusnya sebagai organisasi independen dan netral, diklasifikasikan dalam Global Civil Society karena perjuangannya dalam isu kemanusiaan global yang sering terabaikan saat konflik bersenjata, baik internasional maupun internal. ICRC memanfaatkan globalisasi untuk menyebarkan Hukum Humaniter Internasional secara luas.
2. ICRC sebagai Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional
Bagian ini membahas peran ICRC sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional. ICRC, sebagai International Non-Governmental Organization (INGO), tidak mewakili pemerintah suatu negara, tetapi memiliki jangkauan keanggotaan global. Menurut Clive Archer, organisasi internasional adalah struktur formal yang dibentuk atas kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat untuk kepentingan bersama. May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai pola kerja sama lintas negara dengan struktur organisasi yang jelas dan berkelanjutan. ICRC memenuhi kriteria INGO menurut The Union of International Associations, dengan keanggotaan global dan fokus pada isu kemanusiaan. Dengan demikian, ICRC tidak hanya berinteraksi dengan negara, tetapi juga berperan sebagai aktor non-negara yang aktif dalam dinamika hubungan internasional, terutama dalam merespon krisis kemanusiaan yang mungkin tidak mampu ditangani oleh negara secara penuh.
3. Peran ICRC dalam Global Civil Society dan Implementasinya
Global Civil Society membentuk jejaring kerja yang berupaya mengimplementasikan proses demokratisasi, prinsip good governance, pemerataan kesejahteraan, dan prinsip non-kekerasan untuk mengatasi masalah sosial. ICRC, sebagai bagian dari jejaring ini, berkontribusi pada upaya-upaya tersebut melalui aksi kemanusiaan dan penyebaran Hukum Humaniter Internasional. ICRC secara aktif terlibat dalam merespon konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Organisasi ini bekerja secara simultan dengan berbagai aktor dan organisasi lain untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai universal. Perannya dalam Global Civil Society menunjukkan bagaimana organisasi non-negara dapat memainkan peran penting dalam isu-isu global, khususnya dalam konteks konflik dan kemanusiaan. Keberadaan dan peran ICRC memperkuat gagasan bahwa aktor non-negara memiliki ruang dan kekuatan untuk berkontribusi pada solusi masalah-masalah internasional.
V.Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran ICRC dalam program RFL di Aceh (1989-2005). Analisis data kualitatif dilakukan untuk memahami dampak program tersebut terhadap korban konflik dan keluarga mereka yang terpisah.
1. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada peran ICRC dalam konflik bersenjata di Aceh melalui program Restoring Family Links (RFL). Batasan materi difokuskan pada program RFL, sementara batasan waktu penelitian adalah antara tahun 1989 hingga 2005. Periode ini dipilih karena menandai eskalasi konflik yang tinggi dan fluktuatif, sehingga potensi pemisahan keluarga dan hilangnya kontak antar anggota keluarga sangat besar. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus menganalisis peran ICRC dalam konteks tersebut dan tidak membahas aspek lain dari konflik Aceh atau operasi ICRC di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak program RFL ICRC dalam konteks konflik bersenjata Aceh, selama periode waktu yang spesifik di mana eskalasi konflik dan pemisahan keluarga sangat tinggi.
2. Jenis dan Metode Penelitian
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif fokus pada identifikasi sifat dan karakteristik suatu kelompok, benda, atau peristiwa, tanpa menggunakan metode statistik. Penulis mengutip Mayer dan Greenwood mengenai dua jenis penelitian deskriptif: kuantitatif dan kualitatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan metode statistik, maka dikategorikan sebagai deskriptif kualitatif. Penulis juga merujuk pendapat Miles dan Huberman tentang analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah. Analisis data kualitatif digunakan karena data empiris yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan rangkaian angka-angka. Tujuannya adalah untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam program Restoring Family Links ICRC dalam konflik Aceh.
3. Analisis Data
Proses analisis data meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data melibatkan proses penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan. Peneliti mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data dilakukan untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam program Restoring Family Links yang dilakukan ICRC di Aceh. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penganalisis kualitatif mencari makna, pola, dan penjelasan dari data, serta menguji kebenaran, kekukuhan, dan kecocokan makna tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan teks, bukan angka-angka. Dengan demikian, analisis difokuskan pada interpretasi makna dan pola dari data yang dikumpulkan untuk memahami peran ICRC dalam konteks program Restoring Family Links di Aceh.
VI.Kesimpulan
Skripsi ini menyoroti pentingnya peran ICRC dalam memberikan aksi kemanusiaan di Aceh melalui program Restoring Family Links (RFL). Program ini terbukti efektif dalam membantu korban konflik untuk berhubungan kembali dengan keluarga mereka. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Hukum Humaniter Internasional dan peran Global Civil Society dalam mengatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata.
1. Peran ICRC dalam Konflik Aceh melalui Program RFL
Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa ICRC memainkan peran penting dalam konflik bersenjata di Aceh melalui program Restoring Family Links (RFL). Program ini membantu korban konflik, baik sipil maupun kombatan, untuk tetap terhubung dengan anggota keluarga mereka yang terpisah. ICRC, sebagai organisasi internasional yang netral dan tidak memihak, bekerja berdasarkan mandat internasional dan hukum humaniter internasional untuk memberikan perlindungan kepada korban konflik. Program RFL dilakukan melalui berbagai metode, seperti pertukaran pesan Palang Merah dan kunjungan keluarga ke tahanan, yang terbukti efektif dalam memulihkan hubungan keluarga yang terputus akibat konflik. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran ICRC dalam situasi konflik yang kompleks, khususnya dalam memberikan dukungan psikologis dan kemanusiaan bagi para korban.
2. Pentingnya Hukum Humaniter Internasional dan Aksi Kemanusiaan
Kesimpulan ini juga menekankan pentingnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai landasan bagi operasi kemanusiaan ICRC di Aceh. HHI memberikan kerangka hukum bagi perlindungan korban konflik dan panduan bagi ICRC dalam menjalankan program RFL. Kemajuan teknologi persenjataan yang meningkatkan dampak kerusakan dalam konflik semakin menegaskan perlunya HHI dan aksi kemanusiaan. Pendekatan HHI memberikan dasar bagi tindakan ICRC dalam membantu korban konflik dan keluarga mereka. Program RFL ICRC di Aceh merupakan contoh nyata dari implementasi prinsip-prinsip HHI dalam situasi konflik. Peran ICRC dalam konflik bersenjata menekankan pentingnya komitmen terhadap aksi kemanusiaan dan perlindungan korban tanpa diskriminasi.
3. ICRC sebagai Aktor Global Civil Society
Penelitian ini juga menunjukkan peran ICRC sebagai aktor dalam Global Civil Society. ICRC, sebagai organisasi non-negara, bekerja secara independen dan memanfaatkan kekuatan globalisasi untuk menyebarkan HHI dan memberikan bantuan kemanusiaan. Peran ICRC dalam Global Civil Society menunjukkan bagaimana aktor non-negara dapat berperan aktif dalam dinamika hubungan internasional dan merespon krisis kemanusiaan. Keterlibatan ICRC dalam konflik Aceh dan program RFL memperkuat peran organisasi ini dalam memberikan perlindungan kepada korban konflik dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global. Kesimpulannya, peran ICRC dalam konflik Aceh melalui program RFL menunjukkan efektivitas aksi kemanusiaan dalam situasi konflik dan pentingnya peran aktor non-negara dalam merespon krisis kemanusiaan.
