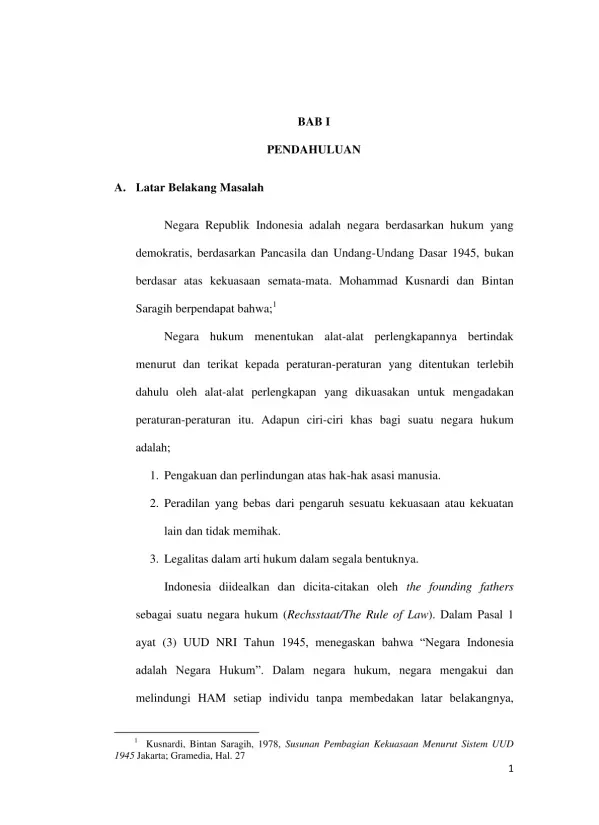
Penerapan Prinsip Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Informasi dokumen
| Sekolah | Universitas Tidak Diketahui |
| Jurusan | Hukum |
| Tempat | Tidak Diketahui |
| Jenis dokumen | Skripsi/Tesis |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 330.41 KB |
- Negara Hukum
- Hak Asasi Manusia
- KUHAP
Ringkasan
I.Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM di Indonesia
Indonesia, sebagai negara hukum (Rechtsstaat/Rule of Law) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu. Prinsip equality before the law menjadi landasan penting dalam penegakan hukum, memastikan semua warga negara, termasuk tersangka, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran HAM yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.
1. Indonesia sebagai Negara Hukum
Dokumen ini mengawali dengan penegasan cita-cita founding fathers Indonesia untuk membangun negara hukum (Rechtsstaat/Rule of Law). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep ini menjadi landasan penting karena negara harus mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu tanpa diskriminasi, menjamin prinsip equality before the law. Artinya, semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Pengakuan dan perlindungan HAM menjadi konsekuensi logis dari penerapan ideologi hukum dalam bernegara, di mana hukum mengikat setiap tindakan warga negara dan negara wajib memberikan timbal balik dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan publik. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang serius akan mengakibatkan pelanggaran HAM, yang bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.
2. Hak Asasi Manusia HAM dan KUHAP
Bagian ini menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada perbedaan perlakuan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum sendiri. Semua adalah warga negara dengan kedudukan dan kewajiban yang sama di depan hukum – yaitu mencari kebenaran dan keadilan. Pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa pengecualian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya UU No. 8 Tahun 1981, menjadi acuan utama dalam praktik hukum pidana materil dan mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). KUHAP secara spesifik mendefinisikan tersangka (Bab VI, Pasal 50-68), dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi, harkat, dan martabat tersangka sebagai manusia. Perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka tak dapat dipisahkan dari penegakan hukum yang adil. Harkat dan martabat merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, termasuk hak dan kewajiban asasi. Martabat sendiri didefinisikan sebagai tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan terhormat. Pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP menjelaskan tersangka sebagai seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan tidak dapat dijadikan objek pemerasan.
3. Pandangan tentang Perlindungan Hukum Tersangka dan HAM
Dokumen ini mengutip pendapat Van Bammelen yang menggambarkan proses peradilan pidana sebagai suatu 'pertarungan' antara tersangka/terdakwa dengan negara. Oleh karena itu, garansi Hak Asasi Manusia (HAM) harus diperkuat agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Meskipun ada jaminan perlindungan hukum bagi tersangka, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. KUHAP sendiri, melalui konsideran huruf ‘c’, menekankan pentingnya menempatkan tersangka dalam posisi yang menghargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Namun, praktik di lapangan seringkali mengabaikan HAM tersangka, yang seharusnya melekat sejak dalam kandungan. Dokumen ini menegaskan definisi HAM sebagai hak asasi/kodrat/mutlak milik umat manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, yang diiringi dengan kewajiban. Bahkan, dalam beberapa ketentuan hukum, seseorang bisa memiliki hak tertentu sebelum lahir dan setelah meninggal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 7) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (Pasal 26) PBB juga menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak tersangka dan tidak menghambatnya dalam memperoleh hak-haknya.
II.KUHAP dan Perlindungan Hukum terhadap Tersangka
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, menjadi pedoman dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. KUHAP menjabarkan definisi tersangka (Pasal 50-68) dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, bahkan bagi seorang tersangka. Meskipun KUHAP menjamin perlindungan hukum terhadap tersangka, pelaksanaannya di lapangan masih seringkali mengabaikan HAM.
1. KUHAP sebagai Pedoman Hukum Acara Pidana
Dokumen ini membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan dan praktik hukum pidana di Indonesia. KUHAP mengatur seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, banding ke pengadilan tinggi, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Definisi tersangka dijabarkan secara khusus dalam Bab VI KUHAP (Pasal 50 sampai Pasal 68), menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penting untuk dicatat bahwa meskipun diduga sebagai pelaku tindak pidana, seorang tersangka tidak boleh dijadikan sebagai objek pemerasan.
2. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam KUHAP
Meskipun dihadapkan pada proses hukum yang bisa diartikan sebagai 'pertarungan' dengan negara (menurut Van Bammelen), KUHAP secara prinsip menjamin perlindungan hukum bagi tersangka. Status tersangka tidak menghilangkan hak asasi, harkat, dan martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum ini tak dapat dilepaskan dari aturan-aturan hukum yang menjamin penegakan hukum yang adil. Harkat dan martabat merupakan nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dibekali daya cipta, rasa, dan karsa, serta hak dan kewajiban asasi. Martabat diartikan sebagai tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan terhormat. KUHAP menegaskan komitmennya untuk melindungi harkat dan martabat manusia melalui tujuan yang ingin dicapai, seperti yang tertera dalam konsideran huruf ‘c’. Tersangka harus diperlakukan sesuai nilai-nilai luhur kemanusiaan, meskipun di lapangan, praktik penegakan hukum terkadang mengabaikan hal ini. Hak asasi manusia, yang melekat sejak dalam kandungan, harus dihormati dan dilindungi.
3. Pasal 52 dan 117 KUHAP serta Hak Tersangka
Pasal 52 dan 117 KUHAP menekankan pentingnya perlindungan HAM tersangka. Pasal 52 menyatakan tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 117 menegaskan keterangan tersangka dan saksi harus diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apa pun. Untuk menghindari penyimpangan hukum, tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, dan aparat penegak hukum wajib mencegah paksaan atau kekerasan selama proses penyidikan. Yahya Harahap menjelaskan keterkaitan erat Pasal 52 dan 117 KUHAP dengan nilai-nilai HAM, khususnya the right of non self-incrimination, yaitu hak tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Keterangan tersangka hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri (Pasal 189 ayat 3 KUHAP). Dalam hukum acara pidana, pengakuan tersangka bukan lagi alat bukti utama (Pasal 184 ayat 1 KUHAP), menunjukkan pengakuan terdakwa, bukan sebagai pengakuan utama. Aparat penegak hukum perlu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya karena berhadapan dengan manusia, pertanggungjawaban kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.
III.Pelanggaran HAM dalam Proses Penyidikan
Praktik penyiksaan dan kekerasan selama proses penyidikan masih terjadi, mengakibatkan pelanggaran HAM serius. Kasus Hambali alias Kemat yang divonis 17 tahun penjara atas kasus pembunuhan Asrori, kemudian terbukti salah tangkap, menjadi contoh nyata. Kasus lain, seperti Ali Gufron (terdakwa Bom Bali) yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengalami penyiksaan, serta pembebasan Jasmani yang menjadi korban salah tangkap di Tulungagung, menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi tersangka. Catatan Kontras antara Juli 2005-Juni 2006 mencatat 140 kasus kekerasan dalam penyidikan. Kasus kematian Tjetje Tadjuddin dan Ahmad Sidiq juga menjadi bukti nyata pelanggaran HAM.
1. Penyiksaan dan Kekerasan dalam Penyidikan
Bagian ini menyoroti masalah serius pelanggaran HAM berupa penyiksaan dan kekerasan yang masih terjadi selama proses penyidikan di Indonesia. Praktik ini sering digunakan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, meski bertentangan dengan prinsip hukum dan HAM. Akibatnya, tersangka mengalami dampak psikologis yang serius, bahkan hingga luka fisik berat dan kematian. Contoh kasus Hambali alias Kemat yang divonis 17 tahun penjara karena pembunuhan Asrori, kemudian terbukti tidak bersalah karena kesalahan penangkapan, menggambarkan betapa seriusnya masalah ini. Kasus Ali Gufron (terdakwa Bom Bali) yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena mengalami penyiksaan fisik selama pemeriksaan, juga menjadi bukti nyata. Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa perilaku kekerasan dalam penyidikan sudah membudaya, terutama untuk mendapatkan pengakuan. Catatan Kontras (Juli 2005 - Juni 2006) mencatat 140 kasus kekerasan selama proses penyidikan. Kasus kematian Tjetje Tadjuddin di Bogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo (2007), serta kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional (Maftuh Fauzi) yang berujung kematian (2008) dan kasus Rimsan dan Rostin di Gorontalo (Mei-Juni 2008) memperkuat fakta ini. Semua kasus tersebut menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin.
2. Kasus Salah Tangkap dan Implikasinya
Dokumen ini juga mencatat kasus salah tangkap yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Salah satu contohnya adalah kasus Jasmani di Tulungagung, Jawa Timur. Ia dijatuhi hukuman penjara 4,5 bulan atas tuduhan pencurian pompa air, tetapi kemudian dibebaskan karena dianggap sebagai korban salah tangkap. Kesaksian terdakwa lain dalam persidangan mengungkapkan bahwa polisi telah salah menangkap pelaku. Jasmani, yang buta huruf, dipaksa mengakui kejahatan dengan membubuhkan cap jempol di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kasus-kasus salah tangkap ini menyoroti perlunya asas kehati-hatian dalam penangkapan tersangka, menimbang kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat serta penegakan hukum. Legalitas tindakan aparat penegak hukum harus selalu mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti yang tertera dalam KUHAP. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, interogasi yang tidak adil, dan penahanan tanpa proses hukum yang adil, semakin banyak terjadi. Proses penyelesaian kasus pun seringkali tidak jelas.
3. Urgensi Pencegahan Pelanggaran HAM dalam Penyidikan
Meskipun terdapat upaya untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penyiksaan, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Padahal, hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas telah dijamin dalam Pasal 52 KUHAP. Pasal 117 KUHAP juga menegaskan pentingnya keterangan yang bebas dari tekanan. Aparat penegak hukum harus mencegah paksaan atau kekerasan dalam proses penyidikan. Kurangnya kesadaran hukum dan kualitas moral aparat penegak hukum juga menjadi faktor penyebab pelanggaran HAM. Semakin tinggi kualitas moral aparat, akan semakin baik pula penegakan hukum dan perlindungan HAM di masyarakat. Kasus-kasus yang diuraikan di atas menunjukkan betapa pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM dalam setiap tahapan proses penyidikan, agar citra penegakan hukum tidak terus diwarnai oleh persepsi negatif seperti perampasan HAM, pemaksaan, dan penganiayaan.
IV.Peran Aparat Penegak Hukum dan Kewajiban Menghormati HAM
Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Mereka wajib menghormati HAM, termasuk hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 52 dan 117 ayat (1) yang menjamin keterangan bebas dari tekanan. Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat. Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang HAM menugaskan lembaga-lembaga negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM. Konsep the right of non self-incrimination juga penting untuk dihormati.
1. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum
Dokumen ini menekankan peran krusial aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Aparat, meliputi kepolisian (penyidik), kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kinerja dan integritas aparat penegak hukum. Selain itu, kesadaran hukum dari subjek hukum (masyarakat) juga menjadi faktor penting penentu keberhasilan penegakan hukum. Keinginan untuk mewujudkan sistem penyidikan ilmiah (Scientific Investigation Method) seringkali terhambat oleh tindakan menyimpang dari pejabat penyidik, seperti penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Hal ini menyebabkan pelanggaran HAM dan citra buruk penegakan hukum. Peningkatan kualitas moral aparat penegak hukum sangat penting untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat dapat merasakan perlindungan hukum yang adil dan terbebas dari pelanggaran HAM.
2. Kewajiban Menghormati Hak Asasi Manusia HAM
Aparat penegak hukum memiliki kewajiban utama untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia dan komitmen internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 7) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (Pasal 26). Semua orang, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak tersangka dan terdakwa, dan tidak boleh menghalangi mereka dalam memperoleh hak-haknya. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM menugaskan lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Presiden dan DPR juga ditugaskan untuk meratifikasi instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kewenangan penyidik yang tercantum dalam KUHAP seharusnya digunakan untuk melindungi HAM warga negara, bukan sebagai alat penindas.
3. Tanggung Jawab Moral dan Intelektual Aparat Penegak Hukum
Dokumen ini menyoroti pentingnya tanggung jawab moral dan intelektual bagi aparat penegak hukum. Mereka harus memahami landasan tanggung jawab dalam tindakan penegakan hukum, karena berhadapan dengan manusia. Rasa tanggung jawab yang kuat perlu dimiliki untuk menumbuhkan dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting untuk menopang kewibawaan dan citra penegakan hukum, dan mengembalikan citra kemurnian penegakan hukum yang selama ini seringkali mendapat citra buruk karena pelanggaran HAM, pemaksaan, dan penganiayaan. Kualitas moral aparat penegak hukum yang tinggi akan secara otomatis membawa perubahan positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat sebagai subjek hukum dan pencari keadilan.
V.Studi Kasus di Polres Batu
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 52 jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka dalam proses penyidikan di Polres Batu, Jawa Timur, dari sudut pandang HAM. Penelitian berlangsung selama satu bulan, mulai 8 November sampai 12 Desember 2013. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan tersangka dan penyidik, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, berkas perkara, literatur, dan peraturan perundang-undangan.
1. Tujuan dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Polres Batu, khususnya di Satreskrim, untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Pasal 52 jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka dalam proses penyidikan, ditinjau dari perspektif HAM. Penelitian difokuskan pada kasus-kasus tindak pidana di mana tersangka mengalami pemukulan. Peneliti berupaya mendapatkan keterangan dari tersangka terkait perlindungan hukum terhadap harkat dan martabatnya selama proses penyidikan di Polres Batu. Penelitian berlangsung selama satu bulan, dari tanggal 8 November hingga 12 Desember 2013. Penelitian menggunakan pendekatan metodologis, sistematis, dan konsisten, menggunakan data primer (wawancara dengan tersangka dan penyidik) dan data sekunder (dokumen, berkas perkara, literatur, dan peraturan hukum).
2. Pengumpulan dan Analisis Data
Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan tersangka dan penyidik kepolisian di Polres Batu. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, majalah, arsip, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan-peraturan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membandingkan peraturan, ketentuan, dan buku referensi, serta data lapangan yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penerapan Pasal 52 jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka dalam proses penyidikan di Polres Batu.
