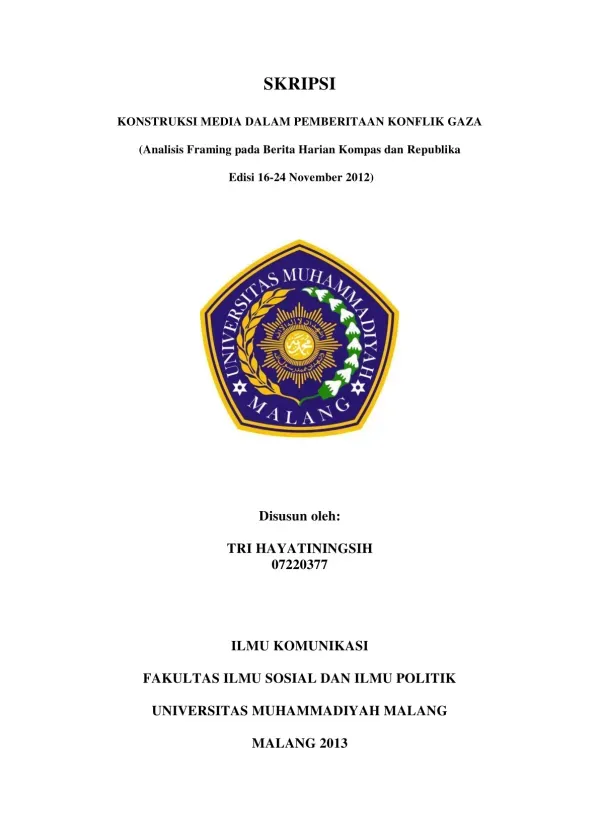
Analisis Konstruksi Media dalam Pemberitaan Konflik Gaza
Informasi dokumen
| Penulis | Tri Hayatiningshih |
| Sekolah | Universitas Muhammadiyah Malang |
| Jurusan | Ilmu Komunikasi |
| city | Malang |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Bahasa | Indonesian |
| Format | |
| Ukuran | 593.52 KB |
- Konstruksi Media
- Pemberitaan Konflik
- Analisis Framing
Ringkasan
I.Komunikasi Konflik dan Peran Media dalam Konflik Gaza
Esai ini meneliti bagaimana media massa Indonesia, khususnya Kompas dan Republika, membingkai (framing) Konflik Gaza dalam pemberitaan mereka. Fokus utama adalah menganalisis konstruksi realitas yang ditampilkan, menilai tingkat objektivitas dalam pelaporan, dan mengkaji bagaimana pilihan bahasa dan strategi penyampaian berita membentuk persepsi publik. Studi ini menggunakan analisis framing dengan model Pan dan Kosicki untuk mengungkap pesan tersirat dalam teks berita. Analisis berita ini menyingkap bagaimana pilihan kata (leksikon), struktur sintaksis, dan elemen grafis berkontribusi pada cara media menyampaikan informasi tentang Konflik Gaza. Peran media sebagai penghubung antar waktu dan pencipta tatanan sosial, khususnya dalam pemberitaan konflik, menjadi sorotan utama. Penelitian ini juga menyinggung konsep jurnalisme dan bagaimana praktik jurnalistik dapat memperpanjang atau meredakan konflik. Peristiwa penting yang dikaji adalah konflik antara Israel dan Hamas pada periode 16-24 November 2012.
1. Definisi Komunikasi dan Konflik
Bagian awal menjelaskan komunikasi sebagai upaya menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik, membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk sebagai bagian dari budaya masyarakat. Selanjutnya, esai ini mendefinisikan konflik sebagai sesuatu yang alamiah dan natural dalam kehidupan manusia, terkadang dipilih secara sadar untuk menyelesaikan masalah. Pilihan untuk menggunakan cara-cara konflik didahului oleh perhitungan untung-rugi. Konflik dijelaskan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia, yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, melibatkan berbagai kalangan, dari elit hingga masyarakat awam. Esai ini juga menyebutkan potensi konflik untuk berdampak luas, bahkan hingga pada disintegrasi sosial dan nasional. Konflik yang berkepanjangan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa. Sebagai contoh, konflik antara Israel dan Hamas di Palestina dijelaskan sebagai contoh konflik yang berkepanjangan dan berdampak internasional, bahkan mengalahkan isu-isu lokal atau nasional selama berminggu-minggu. Konflik ini telah terjadi sejak puluhan tahun, diawali dengan perang Arab-Israel tahun 1948 dan terus berlanjut hingga kini, ditandai oleh berbagai gencatan senjata yang singkat dan kekerasan yang terus berulang. Peran Indonesia dan negara-negara lain dalam upaya gencatan senjata juga dibahas.
2. Peran Media Massa dalam Konflik
Bagian ini menggarisbawahi peran penting media massa dalam membentuk persepsi masyarakat dan mempengaruhi jalannya konflik. Media, menurut Nurudin (2007), turut membentuk masyarakat. Esai ini membahas bagaimana media merekam dan mengkonstruksi peristiwa, serta menangkap realita di balik pemberitaan. Dedy N. Hidayat (2006) dikutip untuk menekankan bagaimana objektivitas dalam pemberitaan dapat menimbulkan wacana tersendiri. Media dipandang sebagai penghubung antar waktu, yang memainkan konstruksi realitas secara piawai. Esai ini menekankan perlunya media massa untuk meliput konflik secara adil dan berimbang, agar masyarakat dunia memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, peran media dalam konflik Gaza antara Israel dan Hamas dijelaskan secara singkat, termasuk peran media dalam menggalang dukungan internasional dan mengupayakan perdamaian. Majalah Intisari dan Harian Kompas disebut sebagai contoh media yang besar dan profesional dalam peliputan berita, khususnya konflik internasional seperti konflik Gaza. Esai juga menyinggung pentingnya media massa sebagai mitra dalam kontrol sosial dan bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi perlu mengaplikasikan nilai-nilai objektivitas dalam proses produksi berita.
3. Konstruksi Realitas dan Framing dalam Berita Konflik
Bagian ini membahas bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial dan membentuk citra (image) dalam benak masyarakat. Penggunaan bahasa tertentu menghasilkan makna tertentu, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menciptakannya. Pandangan konstruksionis yang melihat media sebagai produsen ideologi dominan dibahas, berdasarkan Eriyanto (2008). Media tidak netral, tetapi mencerminkan kekuatan dan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Proses produksi berita dijelaskan, termasuk seleksi, editing, layout, dan penerbitan, menunjukkan adanya rutinitas media (media routine) dan standar penilaian berita masing-masing media. Teori Berger dan Luckmann tentang pemisahan “kenyataan” dan “pengetahuan” dijelaskan sebagai latar belakang pemahaman konstruksi realitas. Beberapa teori tentang konflik, seperti pandangan Barbara Salert dan Charles Tilly, juga dibahas untuk memberikan kerangka pemahaman lebih luas tentang konflik. Peran jurnalis dalam mengurangi atau memperluas konflik dijelaskan. Framing didefinisikan sebagai alat untuk membentuk dan mengemas peristiwa dalam kategori yang dikenal khalayak. Faktor psikologis jurnalis juga dianggap penting dalam proses peliputan. Konsep layak berita menurut Ashadi Siregar diulas, serta pandangan konstruksionis tentang subjektivitas berita yang merupakan hasil konstruksi atas realitas.
II.Objektivitas dan Subjektivitas dalam Pemberitaan Konflik
Bagian ini membahas dilema objektivitas versus subjektivitas dalam analisis berita konflik. Penulis menelaah bagaimana fakta dapat dikonstruksi dan dimaknai berbeda oleh berbagai pihak, mengartikan bagaimana media massa dapat membentuk opini publik. Diskusi mengenai paradigma positivis dan konstruksionis dalam pemberitaan dipaparkan untuk menunjukan bagaimana media, secara sadar atau tidak, membentuk konstruksi realitas. Peran jurnalis sebagai agen konstruksi realitas diulas, bersama dengan analisis elemen-elemen yang membentuk layak berita menurut Ashadi Siregar. Konsep truth, relevance, balance, neutrality dalam mewujudkan objektivitas juga dibahas. Peran Amandemen Kedua UUD 1945 terkait hak memperoleh informasi juga dijelaskan.
1. Objektivitas dalam Pemberitaan Ideal vs Realitas
Bagian ini membahas konsep objektivitas dalam pemberitaan, khususnya dalam konteks konflik. Teks menunjukan bahwa mencapai objektivitas yang sempurna sulit karena fakta seringkali disajikan sebagai realitas simbolik, tidak setara dengan realitas objek. Meskipun berdasarkan fakta, penyajian berita bisa menimbulkan masalah relevansi. Objektivitas dikaitkan dengan faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas, yaitu pemisahan fakta dan opini, seringkali memunculkan wacana baru yang sulit menemukan solusi. Sebuah fakta membutuhkan kebenaran obyektif. Penulis juga membahas bagaimana cara kerja media merekam dan mengkonstruksi peristiwa, mencakup pencarian, pengumpulan, dan penyampaian pesan. Dedy N. Hidayat (2006) dikutip terkait objektivitas fakta dalam pemberitaan yang dapat menimbulkan wacana tersendiri. Esai juga menyinggung kriteria objektivitas menurut Westersthal, yang membaginya menjadi faktualitas (truth dan relevance) dan imparsialitas (balance dan neutrality). Objektivitas sering dihubungkan dengan permasalahan informasi dan berita, dimana fakta bisa berupa realitas pertama (dapat diindra langsung) atau realitas kedua (dikonstruksi oleh pikiran seseorang).
2. Subjektivitas dalam Pemberitaan Konstruksi Realitas dan Perspektif Konstruksionis
Bagian ini berfokus pada aspek subjektivitas dalam pemberitaan, khususnya dalam pandangan konstruksionis. Paradigma ini memandang berita sebagai sesuatu yang subjektif karena merupakan hasil konstruksi atas realitas. Konsep konstruksionisme oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dijelaskan, yang menyatakan bahwa realitas dibentuk dan dikonstruksikan menjadi pemaknaan yang ganda atau plural. Setiap orang bisa memiliki konstruksi realitas yang berbeda. Esai menunjukkan bahwa media massa dapat menggiring khalayak sesuai keinginan melalui berita dan opini. Berita di media dianggap sebagai pelaporan realitas sebenarnya oleh masyarakat, yang memahami media sebagai lembaga netral dan obyektif (sesuai paradigma positivis). Hal ini kontras dengan pandangan konstruksionis, dimana berita bersifat subjektif dan opini tidak dapat dihilangkan. Sudut pandang dan pertimbangan subjektif wartawan memengaruhi pemaknaan realitas. Penulis juga membahas bagaimana penempatan sumber berita, wawancara, dan liputan satu sisi mencerminkan praktik jurnalistik yang subjektif, bukan sekadar kekeliruan atau bias. Amandemen Kedua UUD 1945, khususnya pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga disebutkan sebagai konteks yang relevan.
3. Bias Media dan Pengaruh Ideologi
Bagian ini membahas lebih lanjut tentang bias dalam pemberitaan dan bagaimana ideologi mempengaruhi konstruksi realitas di media. Objektivitas dalam pemberitaan dipandang seringkali terbentur oleh berbagai kepentingan dan bias. Pembentukan ideologi media dipengaruhi oleh latar belakang pemilik media, lingkungan ekonomi dan politik. Lingkungan politik media saat ini tidak hanya fokus pada pencabutan izin operasional, tetapi juga pada kepentingan yang merambah aspek di luar bisnis. Contoh kasus disajikan untuk menggambarkan bagaimana media yang berbeda dapat mewartakan peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda, menonjolkan atau meminimalisir aspek tertentu, bahkan memelintir atau menutup informasi. Kesimpulannya, setiap media tak terlepas dari bias di luar kaidah media. Media seringkali memandang peristiwa dari kaca mata tertentu, membentuk realitas yang dilihat khalayak melalui framing. Teori framing menjelaskan bagaimana jurnalis menyederhanakan, memprioritaskan, dan menstruktur peristiwa untuk dipahami khalayak dalam bentuk berita. Analisis berita pada akhirnya perlu mempertimbangkan faktor psikologis dari jurnalis itu sendiri dalam memahami objektivitas dan subjektivitas dalam pemberitaan.
III.Analisis Framing Berita Konflik Gaza di Kompas dan Republika
Bagian inti dari penelitian ini adalah analisis framing berita Konflik Gaza di dua media besar Indonesia, yaitu Kompas dan Republika. Periode pemberitaan yang diteliti adalah 16-24 November 2012. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi naskah berita dan referensi terkait. Analisis data menggunakan model framing Pan dan Kosicki, dengan memperhatikan struktur sintaksis (headline, latar, kutipan), skrip (gaya bercerita), dan tematik (pemakaian kata, grafis, metafora). Tujuannya adalah untuk mengungkap pesan dan latar belakang ideologis yang mendasari konstruksi realitas dalam pemberitaan kedua media tersebut. Penelitian ini ingin menunjukan bagaimana perbedaan framing di Kompas dan Republika dalam menggambarkan Konflik Gaza.
1. Fokus Penelitian dan Sumber Data
Bagian ini menjelaskan fokus utama penelitian yaitu analisis framing pemberitaan Konflik Gaza di dua media besar Indonesia: Kompas dan Republika. Periode yang diteliti spesifik, yaitu edisi 16-24 November 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pesan dan latar belakang dari teks berita di kedua media tersebut. Sumber data penelitian didapatkan melalui dokumentasi naskah berita dari kedua media tersebut pada periode yang telah ditentukan. Selain itu, referensi jurnal, artikel, dan data lain yang relevan juga digunakan untuk melengkapi data. Analisis berita ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua media tersebut membangun konstruksi realitas mengenai Konflik Gaza dan pesan apa yang ingin disampaikan melalui pilihan kata dan strategi penyampaiannya. Bahasa, sebagai simbol, dianggap sebagai alat untuk mengungkap makna pemikiran penulis berita. Penelitian ini menggunakan interpretasi subjektif yang tetap disesuaikan dengan data secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada analisis isi berita untuk memahami bagaimana Konflik Gaza dikonstruksi oleh dua media besar di Indonesia.
2. Metode Analisis Framing Model Pan dan Kosicki
Bagian ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu analisis framing dengan model yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini mengasumsikan bahwa setiap berita memiliki frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Ide menghubungkan elemen berbeda dalam penyusunan teks berita, sehingga membentuk ‘jendela’ pemaknaan tersirat. Analisis framing ini dilakukan dengan mengamati empat unsur utama dalam sebuah berita: Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Unit Analisis. Struktur Sintaksis diamati dari headline, latar, dan kutipan yang digunakan untuk membangun objektivitas (prinsip keseimbangan dan tidak memihak) dalam penulisan hasil liputan. Skrip merujuk pada cara wartawan mengisahkan fakta, strategi bercerita yang dramatis untuk menarik pembaca. Aspek Tematik mencakup bagaimana wartawan menulis fakta, dimana peristiwa yang diliput, sumber yang dikutip, dan pernyataan yang digunakan untuk mendukung hipotesis yang dibuat. Unsur leksikon (pilihan kata), grafis (huruf tebal, miring, ukuran huruf, gambar), metafora, dan pengandaian digunakan untuk mendukung makna tertentu dalam berita. Model ini memungkinkan analisis secara detail melalui empat unsur tersebut dalam rangka memahami konstruksi realitas yang dibangun oleh media.
3. Aplikasi Analisis Framing pada Berita Kompas dan Republika
Bagian ini menjelaskan bagaimana model analisis framing Pan dan Kosicki diaplikasikan pada berita Konflik Gaza di Kompas dan Republika edisi 15-24 November 2012. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: Struktur Sintaksis, Skrip, dan Tematik. Dalam Struktur Sintaksis, peneliti akan menganalisis headline sebagai topik utama berita, latar berita yang mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan, dan kutipan, sumber, dan pernyataan untuk membangun objektivitas. Analisis Skrip akan melihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta, misalnya dengan gaya bercerita yang dramatis. Sementara Analisis Tematik akan mengkaji pilihan kata, penggunaan grafis, metafora, dan pengandaian yang digunakan oleh wartawan untuk mendukung tema tertentu dan membentuk konstruksi realitas. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk membandingkan bagaimana kedua media tersebut membingkai (framing) Konflik Gaza, mengungkapkan pesan dan latar belakang ideologi yang mendasari konstruksi realitas dalam pemberitaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan pendekatan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Kompas dan Republika dalam memberitakan Konflik Gaza.
